JENGGOT JABAR*
oleh
Mahbub Djunaidi
PERGILAH ke seluruh pelosok Irak. Anda tidak bakal
temui pria berjenggot, kecuali kumis. Apa karena dilarang Saddam Hussein? Sama sekali
bukan. Itu cuma kesenangan dan selera belaka. Paling-paling karena dianjurkan
istri masing-masing. Irak memang berkepentingan dengan ladang minyak, tapi
tidak ada urusan dengan jenggot. Sebaliknya, pergilah ke Iran, Anda akan temui
semua pria berjenggot mulai dari Khomeini sampai tukang bakso. Kenapa? Soalnya karena
kesenangan dan selera. Pria Iran tanpa jenggot sama dengan ayam jago tanpa
jengger, atau seperti ban mobil tanpa dop. Tidak ada aturan bahwa orang Syiah
itu mesti berjenggot dan orang Baath itu hanya boleh berkumis. Berjenggot atau
tanpa jenggot tidak ada hubungannya dengan ideologi dan UUD.
Dan pergilah sekarang ke seluruh kantor Pemda Jawa
Barat, mulai dari pantai hingga ke puncak gunung. Anda tidak akan jumpai
pegawai berjenggot. Kenapa? Apa melanggar Pancasila dan UUD 45? Apa karena
orang berjenggot itu dikhawatirkan korup dan orang tanpa jenggot itu sudah
pasti jujur dan bersihnya? Belum tentu. Berjenggot atau tidak berjenggot itu
tidak ada hubungannya dengan Pancasila dan UUD 45, bahkan tidak ada hubungannya
dengan akhlak. Itu Cuma ada hubungannya dengan peraturan sang gubernur. Karena gubernur
melarang bawahannya berjenggot, maka sirnalah jenggot itu dari tanah Priangan.
Saya sendiri seumur hidup tidak pernah jadi pegawai
negeri, artinya seumur hidup tidak pernah punya NIP. Tetapi, umumnya tetangga
saya pegawai negeri dari segala tingkatan, dan umumnya mereka itu baik-baik dan
punya pembawaan tenang, tidak pernah melompat-lompat dan bertepuk tangan sehingga
menimbulkan gaduh. Mereka baru melompat-lompat dan bertepuk tangan kalau ada
pertandingan sepak bola atau ada suara bakal naik gaji, tidak peduli akan
terjadi segera atau beberapa bulan lagi. Dan menurut data yang saya kumpulkan,
dari 1.000 pegawai negeri yang menjadi tetangga saya itu, cuma tujuh orang yang
berkumis, dan cuma seorang yang berjenggot. Begitu ada larangan gubernur
berjenggot, tetangga saya itu segera membabat jenggot begitu rupa sehingga tidak
ada satu helai rambut pun tersisa.
“Wah, Anda kelihatan sekarang lebih kelimis, seperti
buah ketimun,” kata saya.
“Beginilah pegawai negeri, Mas. Apa larangan orang
atas mesti kita patuhi.”
“Kalau perintah mesti kepala gundul, apa Anda patuhi?”
“Iya dong. Bahkan kalau perintahnya mesti ke kantor
tanpa kepala pun akan saya lakukan.”
“Alhamdulillah. Bergembiralah negeri ini punya pegawai
negeri seperti Anda. Dengan disiplin, kemakmuran dan keadilan sudah dekat di pelupuk
mata.”
MEMANG, antara birokrasi dengan rambut itu ada
hubungannya. Misalnya, raja-raja Tiongkok dari dinasti Han dan Tang semuanya
berkumis yang ujungnya mencuat ke atas. Pendeta-pendeta Budha di zaman itu pun
menirunya. Dengan gaya begitu, mereka berharap bisa tampak lebih garang dan
berwibawa sehingga penduduk bisa dibikin ciut olehnya. Bukankah menakut-nakuti
penduduk itu ada perlunya buat kekuasaan? Tapi, kalau penduduk sudah pada
berani dan tidak mudah digertak, birokrasi pun mencari jalan lain. Misalnya ketika
Tiongkok berada di bawah dinasti Yuan dan Ming, tekniknya pun berubah. Kumis bukan
lagi ujunganya mencuat ke atas, melainkan ganti menjuntai ke bawah. Apa maksudnya?
Maksudnya supaya para birokrat itu kelihatan berkesan prihatin, bijak bestari,
penuh haru melihat penderitaan penduduk, dan tidak doyan duniawi, alergi dengan
duit.
Begitu di Tiongkok, begitu pula di Jepang. Ketika negeri
memasuki era modernisasi zaman Restorasi Meiji tahun 1868, mereka menoleh ke
Jerman dan mencontoh negeri itu. Termasuk potongan kumis. Karena kumis Wilhelm
itu tidak mencuat atau menjuntai melainkan lurus ke samping peralel dengan
lubang hidung, maka para birokrat Jepang pun menirunya. Hanya saja karena suatu
saat kumis belah kanan kaisar Wilhelm tersambar api cerutu sehingga yang belah
kiri pun perlu dipenggal supaya simetris, gaya baru ini tidak sempat ditiru
birokrat-birokrat Jepang.
BUAT Jawa Barat, masalah rambut yang tumbuh di badan
ini bukanlah yang pertama kalinya. Misalnya, di tahun 1973 ramai dibicarakan
perihal rambut gondrong. Dianggap, rambut gondrong itu pertanda berandal dan
ugal-ugalan. Maka mahasiswa diharuskan agar memotong rambutnya. Apakah mereka tunduk?
Ternyata tidak. Dewan Mahasiswa ITB, Padjajaran, Parahiyangan, saat itu menolak
larangan berambut gondrong. Rambut gondrong itu masalah mode dan masalah
selera, tidak ada sangkut pautnya dengan masalah akhlak. Apa mentang-mentang berambut
gondrong lantas orang mesti dianggap brengsek dan tidak tahu aturan? Apa orang-orang
yang rambutnya dipotong rapi itu mesti orang berbudi dan tidak korup? Tidak sesederhana
itu.
Koran kampus Mahasiswa Indonesia saat itu
terbitan September 73 dengan gigih menolak larangan rambut gondrong dengan
paksa. Soal mau gondrong atau mau rambut pendek itu masalah pribadi, itu
masalah mode, itu masalah selera. Jangan mencampuri masalah mode dan selera
pribadi. Bukankah Lasykar Karawang-Bekasi itu gondrong rambutnya? Bukankah Bung
Tomo itu dulu gondrong rambutnya? Bukankah Einstein dan Beethoven dan
Rabindranath Tagore gondrong rambutnya? Siapa berani bilang mereka semua itu
orang-orang brengsek dan tidak tahu aturan?
Saya tidak tahu persis apa yang akan ditulis oleh
koran kampus itu jika masih hidup dan mendengar larangan berjenggot di
daerahnya. Yang jelas, tetangga saya sudah terlanjur bermuka licin seperti
ketimun. Sebagai penduduk saya sekedar berharap, mudah-mudahan muka bersih bisa
menghasilkan pemerintahan bersih. Soalnya, penduduk sudah pandai membedakan apa
yang disebut bersih dan kotor itu. Rakyat tidak tolol.
KOMPAS, 24 JANUARI 1988
*Termaktub dalam "Asal Usul" Mahbub Djunaidi
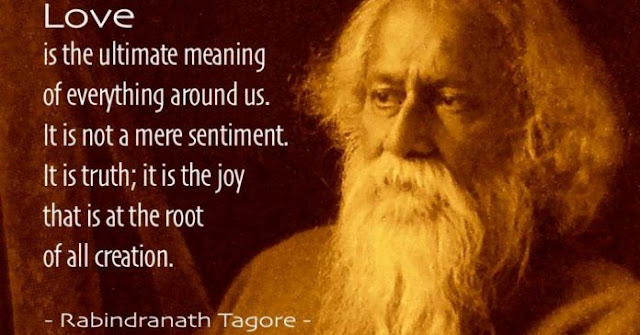



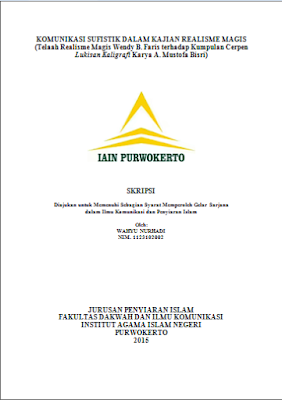
Comments