Pembelaan yang Datang Terlambat
Oleh: Wahyu Noerhadi
Sebetulnya, cukup lama saya ingin mengungkapkan hal ini. Sebab, jika terus-terusan dipendam, rasanya sangat tidak nyaman. Ibarat bersin yang gagal.
Begini: saat ujian skripsi—di kampus
saya disebut dengan istilah munaqosyah—saya betul-betul ingin menanggapi
pendapat, kritik, dan saran dari para penguji atas skripsi saya yang berjudul “Komunikasi
Sufistik dalam Kajian Realisme Magis (Telaah Realisme Magis Wendy B. Faris
terhadap Kumpulan Cerpen Lukisan
Kaligrafi Karya A. Mustofa Bisri)”. Dalam beberapa—sesungguhnya hanya satu—hal,
saya menyetujui saran para penguji atas skripsi saya itu. Terutama soal metodologi
penelitian yang harus dipindahkan ke bab 3, dan tidak lagi di bab 1
(pendahuluan). Pada bagian itu, saya memang keliru, karena menggunakan buku panduan
skripsi yang belum direvisi. Ya, meskipun skripsi yang susun itupun tentunya berdasar
pada referensi skripsi-skripsi sebelumnya, baik dari kampus sendiri maupun
kampus lainnya, semisal UI, UGM, dan UIN SuKa. Dan, karena skripsi saya itu
menggunakan metode penelitian kualitatif (library
research), maka saya pikir penjelasan mengenai metode penelitian itu
disampaikan dengan ringkas di bab pendahuluan. Pikiran saya itu ternyata keliru,
dan saya memang harus menuruti saran dari para penguji untuk memindahkannya di
bab 3. Sehingga profil pengarang (A. Mustofa Bisri) dan gambaran umum kumpulan
cerpen Lukisan Kaligrafi—sebagai dua
hal yang perlu ada dalam komunikasi teks (sastra)—yang tadinya diuraikan di bab
3, sekarang mesti saya pindahkan di awal bab 4.
Kemudian, kritik dari penguji
utama yang menyatakan bahwa pemahaman peneliti (saya sendiri) mengenai salah
satu dampak negatif yang ditimbulkan modernisme—yakni, lahirnya dominasi
ilmu-ilmu empiris-positivistik terhadap nilai-nilai moral dan agama yang
meningkatkan kekerasan fisik dan hadirnya bentuk depresi mental—yang sedikit
saya singgung di bab pendahuluan itu, katanya kontradiktif dengan pemahaman
saya tentang realisme magis yang juga berdasar pada term ‘empiris’. Kata
penguji utama, di satu sisi peneliti menyetujui empirisme dalam cerpen-cerpen
Gus Mus dalam konteks realisme magis, tetapi di sisi lain menolak empirisme
yang menjadi dampak dari modernisasi. Intinya, keduanya berdasar pada
pengalaman, namun mengapa peneliti seolah menolak (ilmu-ilmu) empiris
modernisme. Ya, mendengar itu, saya manggut-manggut dan merasa sangsi antara menyetujuinya
atau tidak. Mengapa demikian? Sebab, sampai saat ini saya masih begitu
kesulitan untuk mengumpul-satukan maksud dari penguji utama itu.
Selanjutnya, saya hakul yakin
bahwasanya kebanyakan—saya ulangi, kebanyakan—penguji skripsi tidak membaca
skripsi mahasiswa yang akan diujinya. “Lagi
pula buat apa repot-repot membaca—apalagi sampai tuntas—skripsi mahasiswa, yang
kami (para penguji) sudah terbiasa menghadapinya. Toh, skripsi mahasiswa hasilnya
tidak jauh-jauh. Seperti itu-itu terus. Dan memang masih banyak pekerjaan yang
lebih penting ketimbang membaca hasil skripsi mahasiswa.” Ya, itulah
pikiran buruk saya. Dan dalam sidang skripsi pun, tak jarang para penguji
melemparkan pertanyaan sekadarnya pertanyaan; bertanya seperti asal bertanya
saja. Formalitas? Yep! Hal itu terbukti saat penguji skripsi saya menyarankan
agar saya hanya mengkaji satu cerpen saja. Padahal, di dalam skripsi itu sudah
saya sampaikan bahwa elemen atau karakteristik realisme magis tidak terwakili
jika hanya dengan mengkaji satu cerpen saja. Maka itu, saya meneliti satu kumpulan
cerpen.
Terakhir, pendapat dari penguji
kedua (sekretaris sidang) yang lebih-kurang mengatakan: “Buat apa Anda meneliti objek (cerpen) yang sudah jelas-jelas bisa
dikatakan atau terkategorikan ke dalam karya realisme magis?” Dan, yang
paling parah, saya disuruh merevisi perumusan masalah dalam skripsi saya itu,
dengan membuang satu pertanyaan tentang kadar realisme magis. Jawabannya—yang mewakili
pertanyaan dan saran dari penguji kedua—seperti ini: Pak, saya mafhum, bahwa karya-karya
yang mengangkat mistisisme Islam sebagai tradisi dalam tasawuf, jika dilihat
dari kacamata Barat memang dikatakan sebagai karya realisme magis, seperti
halnya karya cerpen Danarto. Oleh karena itu, saya meneliti kadar realisme
magisnya; apakah kadar realisme magis dalam kumpulan cerpen Lukisan Kaligrafi—yang disingkat LK—cukup kuat? Itu yang hendak saya tanyakan atau rumuskan
dalam skripsi saya, Pak. Dan hasilnya memang menunjukkan bahwa kumpulan cerpen LK bisa dikatakan karya realisme magis,
dengan kadar yang kuat pada beberapa cerpen, sedang di beberapa cerpen lainnya
kadarnya tidak begitu kuat. Jadi, realisme magis kumpulan cerpen LK itu berbeda dengan novel Midnight’s Children (Anak-anak Tengah
Malam) dan The Satanic Verses (Ayat-ayat
Setan) karya Salman Rushdie, atau One
Hundred Years of Solitude (Seratus Tahun Kesunyian) masterpiece-nya Gabriel Garcia Marquez (Eyang Gabo), yang meraih Nobel
Sastra tahun ’82. Ya, novel-novel yang tergolong ke dalam karya realisme magis diuraikan
secara detail oleh Wendy B. Faris dalam bukunya: Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification of
Narrative (2004), yang mana teori naratif dalam buku itu akhirnya menjadi pisau
analisis yang saya gunakan dalam penelitian.
Ya, begitulah. Tanggapan atau pembelaan
saya ini memang tidak saya sampaikan waktu ujian (sidang) skripsi. Saya baru
bisa mengungkapkannya sekarang. Menyesal memang. Lha mau gimana lagi, wong tiap
kali ngomong saja selalu disela dengan: “Maaf
Mas, saya potong...”. Ya sudah, saya akhirnya iya-iya saja—pura-pura setuju—dan
prosesi sidang skripsi itu memang menjadi lebih cepat. Dan, pembelaan yang datang
terlambat ini, saya tahu, tidak akan mengubah apapun. Nilai, misalnya. Tapi,
soal nilai, toh saya tidak terlalu mementingkannya. Jujur. Selain itu, pembelaan
ini pun memang iseng-isengan saja, barangkali seperti isengnya saya menggarap
skripsi. Bercanda...
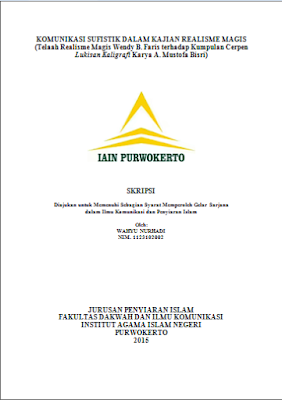 |
| Halaman Judul Skripsi |



Comments