Hidup Hanya Singgah untuk Memandang dan Mendengarkan
Catatan Wahyu Noerhadi
Siang itu, tidak sengaja aku berjumpa dengan seorang kawan di kantin kampus. Duduklah kita; pesan makan-minum, merokok, dan ngobrol.
“Satu waktu pas gue mau liputan di tempat penggusuran, gue iseng-iseng tanya perasaan si ibu yang lapaknya bakal kena gusur. Si ibu itu punya anak tiga, kecil-kecil, dan suaminya nggak tau ke mana. Gue ‘kan sedih, ya. Dan, elu tau apa jawabannya waktu gue tanya perasaan si ibu itu dan bakal gimana setelah lapaknya digusur?”
Pertanyaan yang bukan sungguh pertanyaan. Bang Anto, seorang editor di sebuah media nasional, melanjutkan, “Katanya biasa saja, karena baginya itu hal yang biasa. Si ibu itu bakal cari tempat lain buat lapaknya. Ya, gue liat dan denger sendiri, si ibu itu mengungkapkannya dengan enteng, biasa-biasa saja.”
Bang Anto mengambil jeda, mengisap dan mengembuskan asap rokoknya.
“Nah, kalo pas gitu, kadang—ya, kadang—gue baru sadar Roh Kudus lagi bicara sama gue. Ngajarin gue buat bersyukur. Ya gimana gak bersyukur; gue kerja, kantoran, bisa kuliah lagi. Lu juga. Sedangkan ibu itu?”
“Konsepnya gue rasa sama, Bang?”
“Maksud lu?”
“Ya, di Islam gue sering denger kayak gitu dari cerita-cerita sufi.”
“Oh ya, gue rasa hal-hal kayak gitu, yang kadang kita anggap sepele, justru bisa menambah kadar iman kita. Iya, nggak?”
“Ya, sepakat; melatih kepekaan.”
“Nah, tinggal kita bisa terus peka nggak sama tanda-tanda yang dilimpahkan sama Tuhan.”
“Tanda-petanda-penanda.”
“Ha-ha-ha...”
Obrolan itu terpaksa terhenti ketika Bang Anto diberi kabar lewat telepon oleh Dede kalau dosen sudah sampai di kelas. Dan tugas harus segera dikumpulkan. Kembalilah kita ke dunia yang wadak.
***
Sorenya, aku pergi ke bilangan Cikarang, untuk menjumpai seorang kawan lama sewaktu magang di Jogja. Namanya Zahid Asmara. Zahid sedang ada proyek di pameran lukisan di Jababeka Convention Center selama lima hari. Ia seorang santri dari Pesantren Budaya Kaliopak, Yogyakarta. Zahid berangkat bersama para perupa dari LESBUMI PWNU DIY. Salah satunya Mas Yono—nama kanvasnya Rambat—dengan memamerkan tiga atau empat lukisan di gelaran acara “Indonesian Arts Exhibition” (IAE) itu. Rambat anak kampus ISI Jogja, Fakultas Seni Rupa tentunya. Sedang Zahid anak Filsafat UIN Sunan Kalijaga. Selain menyukai filsafat, ia juga pegiat film. Ia sering menggarap film-film pendek atau pun video dokumenter. Oya, Zahid juga pernah terlibat di film Ziarah, karya B.W. Purba Negara.
Nah, malamnya kami bertiga ngobrol ditemani angin laut, tiga bungkus rokok, dan sebotol Good Day. Sebab tak ada lagi kopi lain, maka minuman rasa permen itulah yang kami beli. Rambat mendominasi obrolan. Ia berkisah tentang Bogowonto, Sadranan, tradisi di desanya, dan bumbu-bumbu lainnya.
“Desa adalah indung, ibu dari segala atau setiap sistem yang ada, yang kini terbentuk dan berjalan. Makanya aku senang ketika ada program ‘Kembali ke Desa’ dari para politisi. Ya, meskipun itu hanya selalu jadi wacana. Ha-ha-ha...”
“Desa adalah ibu. Bapaknya siapa?” Tanya Zahid.
“Mmm, bapaknya adalah konsep.”
“Konsep?”
“Mmm, jadi gini, Hid...”
“Ah, ini mulai ada bumbu-bumbu nih...”
“Bukan, Hid, bukan bumbu. Tapi mecin...”
Kami semua terbahak. Ya, aku hanya mendengarkan, mengangguk, dan ikut tertawa.
“Kamu jarang ‘kan mendengar hal-hal seperti ini di tempat kerjamu?” Rambat menanyaiku.
“Baru tau ini, Mas.”
“Yo, pikiran, omongan seseorang bisa ditinjau dari apa konsumsinya sehari-hari. Juga dari kopinya.”
“Makanan?”
“Konsumsi wacananya.”
Kami kembali tertawa.
“Juga kopinya, sudah pekat atau belum. Itu...”
“Siaaap, siaaap...” Aku dan Zahid menimpali.
“Kita ini harus kembali ke diri; mawas diri, tau diri, harga diri, percaya diri. Kita harus panda-pandai membaca tanda. Tanda-petanda-penanda. Ha-ha-ha... wong aku ini ahli semiotik je...”
“Asuuuu, katanya situ bukan anak kontemporer.” Kata Zahid.
Selesai sarapan siang, aku dan Zahid ke lokasi pameran. Aku melihat-lihat lukisan. Ya, hanya melihat-lihat. Tidak bisa menafsiri. Hanya asal spekalusi; melihat dari jauh, mendekati, dan bilang, “Oh” atau “Waaaah” atau hanya manggut-manggut sok ngerti. Sedang Zahid ambil foto dan video para pengunjung. Ya, Zahid sendirian yang mendokumentasikan kegiatan itu. Dia sudah terbiasa seperti itu—ya, selain kata Rambat dari penyelenggara acara, IAE itu diselenggarakan dengan nekat. Kata Rambat, “Segala kekurangan yang ada dimaklumi saja. Wong IAE ini perdana kok.”
Di sela-sela itu, aku berjumpa dengan Pak Djoko Susilo, salah satu maestro IAE; pelukis jempolan asal Kota Satria, Purwokerto. Di pameran itu, Pak Djoko menampilkan karya lukis potret Gus Dur, Gus Mus, Pak Presiden Jokowi, Ibu Menteri Susi, Einstein, Pak Nasirun, dan lainnya. Oya, Gus Mus dan Pak Nasirun tidak hanya ada di potret. Beliau berdua pun memajang karya-karya lukisnya sendiri di IAE. Gus Mus dengan karyanya yang berjudul “Aksara”, “Membaca”, “Haru Biru”, dan ada juga lukisan karya Gus Mus dengan media klelet rokok yang dipulas di atas amplop-amplop putih. Karya Pak Nasirun, kalau saya tidak salah lihat, ada dua karya dengan ukuran kanvas yang besar-besar. Tapi saya lupa judul dan lupa pula memotret data lukisannya. Ditambah memang tidak ada katalog lukisan dari IAE.
Selain lukisan, di IAE ditampilkan pula patung perunggu, fosil kayu, dan yang kini katanya sedang mulai marak: bonsai. Setelah berputar-putar di beberapa karya itu, saya kemudian berada di antara lukisan karya para pelukis LESBUMI PWNU DIY; ada karya Mas Anzieb, Mas Sony Prasetyotomo, Rambat, Setiyoko Hadi, dan nama-nama lainnya. Nah, di antara lukisan-lukisan itu ada tulisan dari kurator, yakni Mas Anzieb, yang bertajuk “Meletakkan Seni Jauh di Dalam”.
Saya sempat memotretnya pakai kamera handphone. Ada paragraf begini:
“Bukankah kesenian, kebudayaan dan agama yang sejati adalah bermula dari hati yang paling dalam, penuh dengan etika dan syukur nikmat akan keindahan ciptaan-Nya. Maka, dalam meletakkan dan menjalankan kesenian atau sesuatu di dunia ini mari kita memulai dengan terlebih dulu membaca ‘tanda’ (‘tanda-tanda’ yang bersumber langsung dari-Nya) untuk konsumsi hati, bukan untuk konsumsi-konsumsi lainnya yang selesai pada urusan duniawi.”
 |
| Lukisan bertajuk "Merajut Tali Persaudaraan" karya A. Nazilie (2017) |
Siang itu, tidak sengaja aku berjumpa dengan seorang kawan di kantin kampus. Duduklah kita; pesan makan-minum, merokok, dan ngobrol.
“Satu waktu pas gue mau liputan di tempat penggusuran, gue iseng-iseng tanya perasaan si ibu yang lapaknya bakal kena gusur. Si ibu itu punya anak tiga, kecil-kecil, dan suaminya nggak tau ke mana. Gue ‘kan sedih, ya. Dan, elu tau apa jawabannya waktu gue tanya perasaan si ibu itu dan bakal gimana setelah lapaknya digusur?”
Pertanyaan yang bukan sungguh pertanyaan. Bang Anto, seorang editor di sebuah media nasional, melanjutkan, “Katanya biasa saja, karena baginya itu hal yang biasa. Si ibu itu bakal cari tempat lain buat lapaknya. Ya, gue liat dan denger sendiri, si ibu itu mengungkapkannya dengan enteng, biasa-biasa saja.”
Bang Anto mengambil jeda, mengisap dan mengembuskan asap rokoknya.
“Nah, kalo pas gitu, kadang—ya, kadang—gue baru sadar Roh Kudus lagi bicara sama gue. Ngajarin gue buat bersyukur. Ya gimana gak bersyukur; gue kerja, kantoran, bisa kuliah lagi. Lu juga. Sedangkan ibu itu?”
“Konsepnya gue rasa sama, Bang?”
“Maksud lu?”
“Ya, di Islam gue sering denger kayak gitu dari cerita-cerita sufi.”
“Oh ya, gue rasa hal-hal kayak gitu, yang kadang kita anggap sepele, justru bisa menambah kadar iman kita. Iya, nggak?”
“Ya, sepakat; melatih kepekaan.”
“Nah, tinggal kita bisa terus peka nggak sama tanda-tanda yang dilimpahkan sama Tuhan.”
“Tanda-petanda-penanda.”
“Ha-ha-ha...”
Obrolan itu terpaksa terhenti ketika Bang Anto diberi kabar lewat telepon oleh Dede kalau dosen sudah sampai di kelas. Dan tugas harus segera dikumpulkan. Kembalilah kita ke dunia yang wadak.
***
Sorenya, aku pergi ke bilangan Cikarang, untuk menjumpai seorang kawan lama sewaktu magang di Jogja. Namanya Zahid Asmara. Zahid sedang ada proyek di pameran lukisan di Jababeka Convention Center selama lima hari. Ia seorang santri dari Pesantren Budaya Kaliopak, Yogyakarta. Zahid berangkat bersama para perupa dari LESBUMI PWNU DIY. Salah satunya Mas Yono—nama kanvasnya Rambat—dengan memamerkan tiga atau empat lukisan di gelaran acara “Indonesian Arts Exhibition” (IAE) itu. Rambat anak kampus ISI Jogja, Fakultas Seni Rupa tentunya. Sedang Zahid anak Filsafat UIN Sunan Kalijaga. Selain menyukai filsafat, ia juga pegiat film. Ia sering menggarap film-film pendek atau pun video dokumenter. Oya, Zahid juga pernah terlibat di film Ziarah, karya B.W. Purba Negara.
 |
| Suasana Indonesian Arts Exhibition (IAE) di hari terakhir, Minggu (21/01/2018) |
Nah, malamnya kami bertiga ngobrol ditemani angin laut, tiga bungkus rokok, dan sebotol Good Day. Sebab tak ada lagi kopi lain, maka minuman rasa permen itulah yang kami beli. Rambat mendominasi obrolan. Ia berkisah tentang Bogowonto, Sadranan, tradisi di desanya, dan bumbu-bumbu lainnya.
“Desa adalah indung, ibu dari segala atau setiap sistem yang ada, yang kini terbentuk dan berjalan. Makanya aku senang ketika ada program ‘Kembali ke Desa’ dari para politisi. Ya, meskipun itu hanya selalu jadi wacana. Ha-ha-ha...”
“Desa adalah ibu. Bapaknya siapa?” Tanya Zahid.
“Mmm, bapaknya adalah konsep.”
“Konsep?”
“Mmm, jadi gini, Hid...”
“Ah, ini mulai ada bumbu-bumbu nih...”
“Bukan, Hid, bukan bumbu. Tapi mecin...”
Kami semua terbahak. Ya, aku hanya mendengarkan, mengangguk, dan ikut tertawa.
“Kamu jarang ‘kan mendengar hal-hal seperti ini di tempat kerjamu?” Rambat menanyaiku.
“Baru tau ini, Mas.”
“Yo, pikiran, omongan seseorang bisa ditinjau dari apa konsumsinya sehari-hari. Juga dari kopinya.”
“Makanan?”
“Konsumsi wacananya.”
Kami kembali tertawa.
“Juga kopinya, sudah pekat atau belum. Itu...”
“Siaaap, siaaap...” Aku dan Zahid menimpali.
“Kita ini harus kembali ke diri; mawas diri, tau diri, harga diri, percaya diri. Kita harus panda-pandai membaca tanda. Tanda-petanda-penanda. Ha-ha-ha... wong aku ini ahli semiotik je...”
“Asuuuu, katanya situ bukan anak kontemporer.” Kata Zahid.
***
Paginya, jam delapan pameran sudah dibuka. Itu hari terakhir pameran. Jam sembilan-sepuluh masih belum begitu ramai. Akhirnya aku dan Zahid memutuskan untuk sarapan dulu, ngeteh, dan ngerokok lagi. Rambat tidak tampak. Mungkin sedang ngobrol sama pelukis lain.
 |
| Memandang lukisan karya Nasirun, peserta IAE, pelukis yang tergabung dalam LESBUMI PWNU DIY |
Selesai sarapan siang, aku dan Zahid ke lokasi pameran. Aku melihat-lihat lukisan. Ya, hanya melihat-lihat. Tidak bisa menafsiri. Hanya asal spekalusi; melihat dari jauh, mendekati, dan bilang, “Oh” atau “Waaaah” atau hanya manggut-manggut sok ngerti. Sedang Zahid ambil foto dan video para pengunjung. Ya, Zahid sendirian yang mendokumentasikan kegiatan itu. Dia sudah terbiasa seperti itu—ya, selain kata Rambat dari penyelenggara acara, IAE itu diselenggarakan dengan nekat. Kata Rambat, “Segala kekurangan yang ada dimaklumi saja. Wong IAE ini perdana kok.”
 |
| Bersama Pak Djoko Susilo (peserta IAE) dan karyanya, potret Gus Mus |
Di sela-sela itu, aku berjumpa dengan Pak Djoko Susilo, salah satu maestro IAE; pelukis jempolan asal Kota Satria, Purwokerto. Di pameran itu, Pak Djoko menampilkan karya lukis potret Gus Dur, Gus Mus, Pak Presiden Jokowi, Ibu Menteri Susi, Einstein, Pak Nasirun, dan lainnya. Oya, Gus Mus dan Pak Nasirun tidak hanya ada di potret. Beliau berdua pun memajang karya-karya lukisnya sendiri di IAE. Gus Mus dengan karyanya yang berjudul “Aksara”, “Membaca”, “Haru Biru”, dan ada juga lukisan karya Gus Mus dengan media klelet rokok yang dipulas di atas amplop-amplop putih. Karya Pak Nasirun, kalau saya tidak salah lihat, ada dua karya dengan ukuran kanvas yang besar-besar. Tapi saya lupa judul dan lupa pula memotret data lukisannya. Ditambah memang tidak ada katalog lukisan dari IAE.
 |
| "Membaca", lukisan karya Gus Mus |
Selain lukisan, di IAE ditampilkan pula patung perunggu, fosil kayu, dan yang kini katanya sedang mulai marak: bonsai. Setelah berputar-putar di beberapa karya itu, saya kemudian berada di antara lukisan karya para pelukis LESBUMI PWNU DIY; ada karya Mas Anzieb, Mas Sony Prasetyotomo, Rambat, Setiyoko Hadi, dan nama-nama lainnya. Nah, di antara lukisan-lukisan itu ada tulisan dari kurator, yakni Mas Anzieb, yang bertajuk “Meletakkan Seni Jauh di Dalam”.
Saya sempat memotretnya pakai kamera handphone. Ada paragraf begini:
“Bukankah kesenian, kebudayaan dan agama yang sejati adalah bermula dari hati yang paling dalam, penuh dengan etika dan syukur nikmat akan keindahan ciptaan-Nya. Maka, dalam meletakkan dan menjalankan kesenian atau sesuatu di dunia ini mari kita memulai dengan terlebih dulu membaca ‘tanda’ (‘tanda-tanda’ yang bersumber langsung dari-Nya) untuk konsumsi hati, bukan untuk konsumsi-konsumsi lainnya yang selesai pada urusan duniawi.”
Selesai membaca tulisan itu, melihat-lihat lukisan, bertemu
dan ngobrol dengan Pak Djoko, malamnya ngobrol dengan Zahid, Rambat, dan
paginya bersama Bang Anto, seseorang bergumam, “Urip mung mampir nyawang lan
ngerungoke (Hidup hanya singgah untuk memandang dan mendengarkan)”.
Djakarta, 22/01/2017
0.55 WIB


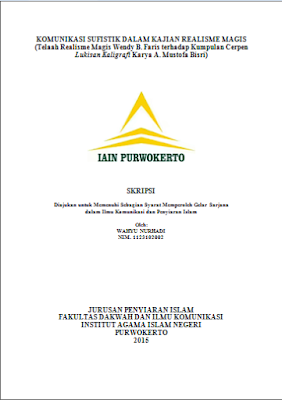
Comments