Isi Kepala Sapto*
Oleh: Wahyu Noerhadi
Ia sudah begitu muak
dengan semuanya. Segala hal yang ada di hadapannya sudah tentu akan dinilai
salah olehnya. Bahkan ketika ia telah sampai di sebuah warung makan,
kemuakannya belum juga sirna.
“Pakai apa, Mas?”
“Telur, Pak.” Sapto menunjuk
dengan dagunya.
“Ceplok, dadar,
telur asin, atau telur puyuh?” Si empunya warung kembali bertanya.
Sapto menjawab
setelah mengembuskan nafas panjangnya. Ia menyerah dan merasa wajib menjawab
pertanyaan itu demi menuntaskan suara nyaring cacing-cacing dalam perutnya. Ia
tak mengerti, mengapa lelaki tua itu harus kembali bertanya padanya. Padahal, ia
sudah menjawab dengan isyarat yang ditunjukkan dagunya. Tapi, Sapto tak sampai
hati melontarkan kekesalannya itu. Karena, ia tahu, hal itu hanya akan
membuang-buang energinya, yang memang hampir habis digerogoti kekesalannya.
Sapto menyantap
sarapan—sekaligus makan siangnya—tanpa selera, lantaran rasa muak itu telah
lebih dulu mengendap dalam dirinya. Ia makan dengan rasa muaknya pada sikap
orang-orang yang tadi ia temui di kampusnya. Dan, ia sedikit terbebas dari
pikirannya itu ketika mendapati bahwa piring di hadapannya telah benar-benar bersih
hingga tak tersisa satu butir pun nasi. Ia meneguk segelas teh manis hangat
hingga tersisa seperempat, lantas melolos sebatang Gudang Garam dari
bungkusnya. Rokok yang sudah terpasang di kedua bibirnya itu segera
dinyalakannya. Bunga api yang terbang dan jatuh di celananya sedikit
mengagetkannya. Asu, gumamnya. Sapto mengisap rokoknya dalam-dalam, dan
mengembuskan asapnya dengan amat pelan. Sesekali ia membentuk asap yang diembuskannya
itu menjadi bulatan-bulatan kecil.
Tentang bulatan-bulatan
kecil itu, Sapto pernah berkomentar—dalam hati tentunya—ke anak-anak SMA yang sedang
merokok di sampingnya, dan asyik membentuk bulatan-bulatan kecil di setiap
embusan asap rokok mereka. Ah, dasar bocah. Merokok saja pakai gaya-gayaan
segala, komentarnya. Dan sekarang, entah disadarinya atau tidak, Sapto
mengikuti gaya merokok mereka.
Sapto berharap,
setiap isapan rokoknya itu dapat membuat kepalanya tenang. Dan benar, ia
sedikit merasa tenang setidaknya sampai isapan kelima. Di isapan keenam, ia kembali
teringat pada setiap kata yang diucapkan oleh orang-orang yang membuatnya muak.
Kemudian, asap yang keluar dari mulutnya seolah membentuk potret-potret peristiwa
antara ia dan orang-orang itu.
***
“Ada apa, Mas?” Tanya
wanita paruh baya dari balik meja kerjanya.
“Mmm, ini Bu. Saya
mau...”
Belum selesai Sapto
bicara, wanita itu menyelanya,
“Lebih baik kamu pulang
dulu. Kami tidak melayani mahasiswa yang tidak bersepatu.”
“Tapi, Bu...”
Sapto tak meneruskan
ucapannya, karena wanita berkacamata tebal itu sudah kembali khusyuk pada layar
komputernya. Sapto masih mematung dan pandangannya terpaku ke arah sandal Swallow
yang dikenakannya. Sapto ingin mengeluarkan kata-kata, tapi ia merasa lidahnya
seketika bertulang. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan ruang Jurusan. Ia
memang harus meninggalkan ruangan itu untuk mendinginkan kepalanya, dan perlu
kembali lagi dengan kata-kata yang tak dapat disela—apalagi dibantah—oleh
wanita itu, atau oleh siapa pun yang membuatnya kesal. Ia menginginkan kata-kata
yang sering dilontarkan para ketua mafia kepada para centengnya. Sapto pun berangan-angan
menjadi Vito Corleone dalam film Godfather. Lengkap dengan mawar merah
di tuksedonya.
Setelah siap dengan
kata-kata dalam kepalanya, Vito Corleone kembali memasuki ruang Jurusan. Namun,
ia tak mendapati sosok wanita berkacamata itu. Barangkali ke kamar mandi, pikirnya.
“Bu Surtinya ada,
Pak?”
“Sedang keluar. Ada
keperluan apa?”
Ya, sebenarnya Sapto
tak perlu menanyakan keberadaan Bu Surti. Harusnya ia bersyukur dengan tidak
adanya wanita itu, yang mungkin akan mengusirnya kembali. Ya, sesungguhnya Sapto
cukup bicara saja dengan pria berambut putih itu, yang berkata tanpa menoleh ke
arahnya. Sapto merasa amat perlu bertemu dengan Bu Surti. Sebab, ia tak mau
jika kata-kata—atau lebih tepatnya alasan mengapa ia tak mengenakan sepatu—yang
telah dipersiapkannya itu nantinya mubazir.
Setelah
menimbang-nimbang, akhirnya Sapto pun terpaksa menyampaikan maksudnya pada Si
Uban.
“Ini, Pak. Saya mau
daftar...”
“Rambutnya bagus ya,
Mas. Panjang dan bergelombang,” Si Uban menyela, “Tapi, dengan rambut sebagus
itu kamu tidak akan mendaftarkan diri buat magang, ‘kan?
Sapto tahu, itu
bukan pujian, melainkan pencelaan. Sapto juga sebenarnya bisa memuji balik Si
Uban dengan: Rambutmu juga bagus, Pak. Putih berkilau. Tapi, Sapto tak
melakukannya. Saat itu, Sapto hanya ingin menyelesaikan urusannya.
“Terimakasih atas
pujiannya, Pak. Iya Pak, saya mau daftar magang di Jogja. Bapak bisa membantu
saya?”
“Tapi, kamu harus
memangkas rambutmu dulu. Mosok, mau magang dengan rambut sesemrawut
itu.”
“Sehabis dari sini
saya akan pergi ke tukang cukur, Pak. Tapi, untuk saat ini tolong bantu saya,
Pak. Mudahkanlah urusan saya. Urusan magang ini, Pak.” Pinta Sapto dengan paras
memelas.
“Ya, saya akan membantumu,
asal setelah ini kamu benar-benar merapikan rambutmu.”
Sapto berpikir bahwa
Si Uban mulai melunak. Tapi, ia keliru.
“Tapi, apakah kamu
sudah memenuhi semua syarat pendaftaran PPL? Bagaimana dengan nilai-nilaimu,
apa sudah lulus semua? Rasa-rasanya, saya kok jarang sekali melihatmu di
kampus. Kamu enggak pernah kuliah, ya?”
“Pak,” suara Sapto meninggi,
“jika saya ke sini hendak mendaftarkan diri untuk keperluan magang, berarti
saya pun telah siap dengan segala persyaratan magang. Bapak harusnya tahu itu!”
“Oh, begitu ya,” Si
Uban menyandarkan punggungnya ke kursi, dan melipatkan kedua tangannya di perut
buncitnya, “Coba perlihatkan berkas-berkasmu!”
Melihat polah Si
Uban, Sapto pun hilang kesabaran.
“Nih, makan
berkas-berkasku! Aku tak membutuhkannya. Aku tak mau lagi memedulikannya.”
Sapto tak
terkendali. Kertas-kertas dalam map kuning di genggamannya itu sudah dihamburkan
ke udara. Si Uban terhenyak, dan bangkit dari kursinya.
“Hey! Apa
yang kamu lakukan?” Si Uban memelototi Sapto, “Biar bagaimana pun, kamu harus
mematuhi birokrasi.”
“Ah, persetan dengan
birokrasi!” Wajah Sapto merah padam.
“Jaga omonganmu dan
ambil kembali berkas-berkasmu itu!”
Kertas-kertas yang
sudah berserakan di lantai itu dipungutnya satu-satu, lantas ia
merobek-robeknya di hadapan Si Uban. Kemudian, dengan dada yang bergejolak ia
keluar dari ruang Jurusan.
Di tangga, ia
bertemu dengan Bu Surti.
“Kenapa kau masih
mengenakan sandal?”
Sapto dan Bu Surti terdiam
dengan jarak 6 anak tangga. Bu Surti menunggu jawaban Sapto. Tapi, Sapto takkan
menjawab pertanyaan itu. Ia sudah lupa alasan yang tadinya akan dilontarkan
pada wanita itu. Ia sudah tak bisa berpikir lagi. Saat itu, ia hanya tahu cara
meluapkan kegeramannya. Sapto hanya melepaskan sandalnya yang sebelah kiri,
lantas melemparkannya tepat ke muka wanita berkacamata itu.
Wanita itu masih memegangi
mukanya. Rupanya, sandal yang dilemparkan Sapto itu cukup membuat mukanya
pedas. Sapto tak berkata apa-apa. Ia menuruni anak tangga, memungut sandalnya,
dan berlalu meninggalkan kampusnya. Beberapa mahasiswa yang melihat kejadian
itu amat terheran. Mereka bertanya-tanya, tapi segan untuk saling bertanya. Mereka
hanya memandangi langkah Sapto yang tergesa.
Sapto mengendarai
Vespa kalengnya dengan kepala yang kacau, dada yang kacau, dan esok yang kacau.
Ia tak tahu, bagaimana harus membereskan kuliahnya. Tentu, ia tak mungkin meminta
maaf pada kedua orang itu. Ia berpikir, bahwa perbuatannya itu adalah pelajaran
untuk Si Uban dan Bu Surti. Ia malah berpikir, seharusnya mereka berdualah yang
meminta maaf dan berterimakasih kepadanya. Sapto berharap, mereka seharusnya
mampu melayani mahasiswa. Karena, pikir Sapto, mereka pun digaji oleh
mahasiswa. Mereka dapat duit dari mahasiswa. Mereka bekerja untuk melayani
mahasiswa. Maka itu, mereka tidak seharusnya bertingkah semena-mena pada
mahasiswa. Dengan kejadian itu, ia berharap nantinya Si Uban, Bu Surti, atau para
birokrat di kampusnya tidak mengulangi kesalahan yang serupa pada mahasiswanya,
pada adik-adik angkatannya. Ya, Sapto masih angkuh dengan pikirannya. Ia merasa
puas telah mendapatkan analisa semacam itu.
Di jalan, ia bertemu
pemuda yang mengendarai sepeda motornya dengan ugal-ugalan. Laju kendaraan pemuda
itu memakan jalur Sapto. Hal itu cukup mengagetkan Sapto, hingga membuat Vespanya
oleng. Namun tak sampai terjatuh. Sapto berpikir, apakah ia harus memutar-balik
arah. Ya, Septo memutar-balik motornya dan berusaha mengejar motor pemuda itu.
Setelah Vespanya itu berada sejajar dengan motor pemuda itu, Sapto menendang tubuh
pemuda itu dengan amat keras, dengan kaki kiri. Motor itu seketika
bergoyang-goyang, roboh dan berselancar sebentar di aspal, kemudian mendarat di
got.
“Asuuuu, Kowe!”
Serapah pemuda itu pada Sapto.
Sapto menoleh ke
belakang dan melemparkan senyum paling kecut padanya. Ya, pemuda itu hanya
mampu menyumpah-serapahi Sapto. Ia tak mungkin mengejar Sapto dengan kondisi
motor dan tubuh seperti itu.
***
Sapto tersenyum dan
menggeleng-gelengkan kepalanya membayangkan semua itu.
“Sudah, Pak. Jadi
berapa?”
Ia keluar dari
warung makan dengan perasaan yang aneh dan tak keruan. Ia muak sekaligus malu.
Purwokerto, 2014
*Dimuat di Koran Pantura, edisi Selasa 17 Mei
2016.



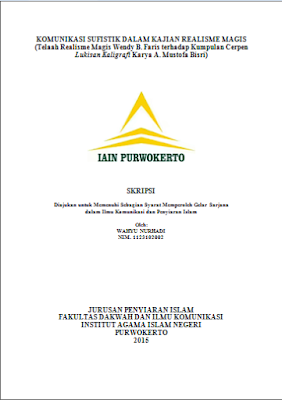
Comments