Segalanya (memang) tentang Proses
oleh
Wahyu Noerhadi
Di sebuah workshop atau kelas-kelas kepenulisan, mungkin akan
selalu ada pertanyaan seperti ini: “Bagaimana sih cara membuat tulisan yang
baik?”. Ya, pertanyaan semacam itu barangkali sering atau setidaknya pernah
muncul di batok kepala kita—yang berkeinginan jadi penulis. Pertanyaan itu
merupakan pertanyaan penting dan klise. Setelah saya cari tahu, ternyata
jawabannya amatlah simpel. Kalau tidak keliru, saya pernah dengar Pram, ketika
mendapatkan pertanyaan seperti di atas, beliau menjawab: “Nulis, nulis
saja!”
Saya sepakat dengan jawaban simpel itu. Saya pikir, segalanya memang
tergantung pada diri kita. Nasib ada di kita. Kita tidak mungkin jadi penulis,
jika tiap hari kerjaan kita memukuli orang. Jika kita lebih gemar memukuli
orang, sepertinya kita lebih cocok jadi preman atau pegulat ketimbang penulis.
Ya, jika kita betul-betul ingin jadi penulis maka kita hanya perlu menulis,
menulis, dan menulis. Menulis kapan pun dan di mana pun, kecuali dalam waktu
dan tempat-tempat tertentu. Misal, kita tentu tidak bisa menulis ketika sedang
sembahyang. Kita juga sepertinya dilarang menulis ketika sedang berada di
toilet pom bensin. Terlebih di toilet lawan jenis. Intinya, kata Sori Siregar,
kita hanya butuh menulis. Kita tidak perlu menunggu move on dari
kegalauan lantaran diputus pacar, untuk menulis. Kita tidak perlu mood untuk
menulis. Kita tidak perlu menunggu ilham apalagi wahyu ketika hendak menulis.
Lagipula kita bukan wali atau nabi. Kita tidak perlu ini-itu, kita hanya perlu
menulis. Tulislah segala hal yang kita lihat, dengar, pikirkan dan rasakan.
Mustahil rasanya kita kehabisan bahan buat ditulis. Karena, saya rasa, semua
hal bisa ditulis.
Ya, mungkin kita tidak bisa langsung membuat tulisan secantik karya-karyanya
Alm. Gabriel Garcia Marquez, yang akrab disapa Gabo itu. Tapi tenang saja,
menurut saya, itu cuman soal proses. Jika kita rajin membaca dan disiplin
menulis, maka bukan tidak mungkin kelak kita mampu menghasilkan tulisan atau
karya yang ciamik. Jadi, sekali lagi: nulis, nulis saja! Kita tidak
perlu bersusah-payah memikirkan tema-tema besar agar menghasilkan karya yang
baik. Kita bisa saja berangkat dari hal-hal yang remeh-temeh. Seperti yang
sudah dan sering dilakukan Gabo. Lihatlah cerpennya yang bertajuk “Putri Tidur
dan Pesawat Terbang” itu! Di cerpennya itu, beliau bercerita tentang seorang
pemuda—mungkin dirinya sendiri—yang tergila-gila dengan keelokkan seorang gadis
yang duduk di sampingnya, di pesawat. Ya, saya pikir, cerpen itu begitu
sederhana, tapi amat menarik. Meski temanya sederahana, tapi akibat pengelolaan
yang apik akhirnya cerpen itu mampu mengoyak-ngoyak perasaan pembaca, dan
sedikit menyindir takdir. Beliau bisa menuliskan atau menceritakan
pengalamannya dengan renyah, dan mampu membikin pembaca betah. Saya pun sering
mendapati makhluk yang ayunya melebihi Dian Sastro di kereta, di bis, di
angkot, di mana pun. Saya pun ingin menuliskannya seperti yang dilakukan oleh
Gabo, tapi untuk saat ini saya masih pesimis atau belum yakin dapat
menceritakannya sebaik dan semahir Eyang Gabo. Ya, sepertinya lagi-lagi itu soal
proses. Saya kira, tak hanya perkara menulis, dalam bidang apa pun butuh proses
untuk mencapai kemahiran serta kesuksesan.
Barangkali, saat ini saya juga bisa menyimpulkan bahwa kehidupan pun
merupakan proses. Proses menuju kepunahan. Ya, segalanya adalah proses. Karena
kehidupan adalah proses, lantas bagaimana proses kehidupan yang direka oleh
Lilis dalam kumpulan cerpennya. Mari kita barang sejenak mencermati kesepuluh
cerpen yang dibikin Lilis. Ya, ada beberapa proses kehidupan cerpen yang
menarik bagi saya. Seperti yang bisa kita saksikan di cerpen Trilogi “Hibernasi”.
Ketiga cerpen itu membahas tentang mimpi; tentang beberapa orang yang memiliki
kemampuan menjelajahi alam mimpi orang lain. Saya pikir, tema cerpen itu pun
menarik. Karena, setahu saya, tema tentang mimpi memang masih jarang digarap
oleh pengarang lain. Lewat cerpen itu, Lilis terlihat asyik-masyuk bermain
dengan imajinasinya. Hingga saya terseret arus imajinasinya. Namun, saya rasa,
ketiga cerpen itu ‘enaknya’ memang dibuat cerbung saja—dengan judul
“Hibernasi”, mungkin. Sebab, ketiga cerpen itu memang memaksa untuk dibuat
cerbung; ending di cerpen “Hibernasi I” dan “Hibernasi II” itu amatlah
menggantung. Selain Trilogi “Hibernasi”, ada lagi cerpen yang lumayan menarik,
judulnya “Wanita Suci Titipan Tuhan”. Cerpen itu menggambarkan proses kehidupan
di tahun 2050; bagaimana padatnya penduduk bumi, yang kemudian memaksa para
wanita untuk tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Wanita-wanita itu
adalah wanita yang memiliki tanda atau cap di punggung tangan kanannya. Cap itu
bertuliskan: Wanita Suci Titipan Tuhan.
Saya juga tertarik pada cerpen yang bertajuk “Buku Kelimapuluh Nayla”.
Saya tertarik karena dalam cerpen ini latar yang digunakan oleh Lilis bertempat
di Paris—kota yang katanya begitu romantis. Saya pikir, beberapa cerpen Lilis sudah
baik. Lewat cerpennya, Lilis mampu menyeret saya dan mungkin pembaca lainnya ke
dalam imajinasinya; ia mampu memprediksi masa depan, dengan
kemungkinan-kemungkinan yang mungkin; ia juga mampu mengajak pembaca ke Paris,
dengan detail-detail tempat yang ia deskripsikan. Saya tak tahu benar-tidaknya
detail-detail yang disampaikan Lilis. Tapi, anggaplah benar seperti itu adanya.
Selanjutnya, untuk cerpen-cerpen lainnya, saya kira penggarapannya masih belum
maksimal. Di cerpen lainnya, Lilis menghadirkan tema tentang penantian,
kisah-kisah merah jambu, atau tentang cinta yang tak terbalaskan. Ya, memang
tema-tema yang klise. Tapi, sebetulnya tidak masalah juga jika Lilis
mengungkapkannya dengan menarik, meski tema cerpen itu banyak dipakai oleh
pengarang lain. Berarti, di sini pengungkapan (bentuk) adalah koentji. Karena
memang sudah terlalu banyak tema yang sama yang digarap pengarang lain, maka sekarang
kita tinggal memainkan teknik untuk menciptakan bentuk atau cara ungkap yang
berbeda. Selain tema yang klise dan teknik yang kurang menarik, Lilis juga sepertinya
kurang fokus pada sudut pandang (point of view) penceritaannya. Dalam
beberapa cerpen, Lilis seolah hendak mencampuri urusan orang-orang ciptaannya.
Mungkin, lantaran sudut pandang yang kurang fokus tadi akhirnya saya merasa begitu
kesulitan membedakan antara suara Lilis dan suara orang-orang ciptaannya. Saya
melihat dan mendengar seolah Lilis dan orang-orang ciptaannya itu sedang
berebut suara. Ya, kita tahu, semua suara dalam kumpulan cerpen ini pada
hakikatnya adalah suara Lilis. Tapi, bukankah Lilis telah memberikan hidup dan
kehidupan pada tokoh-tokoh dalam cerpennya. Memang alangkah lebaih baik dan
bijaknya jika Lilis membiarkan saja tokoh-tokoh yang dibuatnya itu untuk bersuara
dan bercerita. Dan Mochtar Lubis pun pernah mengatakan, biarkan tokoh-tokoh
yang kita (pengarang) ciptakan menyampaikan pikiran dan sikapnya sendiri. Kita
tidak bisa serta-merta mengaturnya. Karena, kita juga bukan Tuhan. Kemudian,
saya rasa, Lilis pun kurang menguatkan karakter tokoh-tokoh dalam beberapa
cerpennya. Ada beberapa tokoh yang—saya lupa nama-namanya—memiliki karakter
aneh. Tokoh itu memiliki emosi yang bisa seketika berubah seratus delapanpuluh
derajat. Tokoh yang awalnya angkuh dan sinis, seketika sikapnya bisa melentur.
Ya, mungkin ada orang-orang yang memiliki sifat layaknya tokoh yang diciptakan
Lilis itu. Tapi, tetap saja, saya seperti melihat adanya keanehan.
Selanjutnya, ada satu hal yang nampaknya perlu dikurangi kadarnya oleh
Lilis dalam meramu cerpen, yaitu kadar dakwah. Entah disadari atau tidak oleh
Lilis, saya rasa, ada dua cerpen yang sering menyuratkan pesan-pesan kebajikan
dengan begitu gamblang. Pesan-pesan itu kadang berbarengan disampaikan oleh
narator, juga oleh tokoh-tokoh dalam cerpennya. Judul kedua cerpen itu “Cermin
Hati” dan “Tuhan pun Tahu”. Terakhir, saya lihat Lilis rasanya kurang teliti
atau kurang peduli pada cerpennya. Hampir di semua cerpennya terdapat berbagai
kesalahan penulisan kata atau frasa. Padahal, setahu saya, seorang penulis
sudah sepatutnya teliti dan peduli pada tulisannya. Sebab, tulisan adalah
anak-anak rohani penulisnya. Husnudzhon saya, barangkali Lilis sedang
terburu-buru.
Ya, itulah sedikit pembacaan saya—yang mungkin keliru—terhadap kumpulan
cerpennya Lilis. Saya senang karena sudah ada sepuluh anak rohani yang
dilahirkannya. Berarti, besok atau besok-besok bakal ada lagi anak yang
kesebelas, duabelas, tigapuluh, limapuluh, seratus, dan seterusnya. Itu harapan
saya. Mengenai tema, bentuk, sudut pandang, dan lainnya, saya rasa, kita perlu
berpijak pada kata-kata Danarto pada Temu Sastra tahun 1982: Proses, proses,
proses, proses, proses, proses, proses...
Purwokerto,
Januari 2015
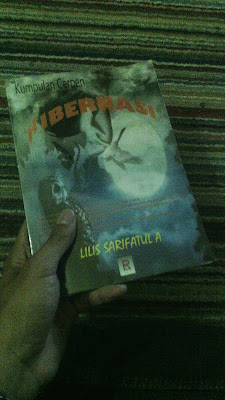



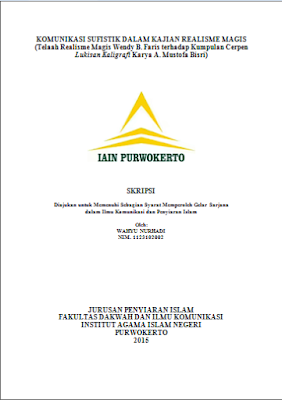
Comments