Sedikit Cerita dari Kawanku
Oleh: Wahyu Noerhadi
Akhirnya aku berjumpa lagi dengannya di kantin kampus. Sebenarnya, aku tidak menduga akan kembali berjumpa dengannya, meski aku pun mafhum, tiap pagi ia dan kawan-kawannya bakal nongkrong dan memesan ‘sesajen’ (kretek dan kopi hitam) di sini. Kini ia memang tampak lebih kurus ketimbang waktu kami masih sering bersama, ketika kami masih semester 3. Selain lebih kurus, janggutnya pun terlihat lebih lebat. Namun, ada satu yang tidak berubah darinya, yaitu penampilannya. Ya, penampilannya itu—yang kerap membuat orang barang sejenak tak bisa mengalihkan pandang padanya—selalu saja perlente.
Akhirnya aku berjumpa lagi dengannya di kantin kampus. Sebenarnya, aku tidak menduga akan kembali berjumpa dengannya, meski aku pun mafhum, tiap pagi ia dan kawan-kawannya bakal nongkrong dan memesan ‘sesajen’ (kretek dan kopi hitam) di sini. Kini ia memang tampak lebih kurus ketimbang waktu kami masih sering bersama, ketika kami masih semester 3. Selain lebih kurus, janggutnya pun terlihat lebih lebat. Namun, ada satu yang tidak berubah darinya, yaitu penampilannya. Ya, penampilannya itu—yang kerap membuat orang barang sejenak tak bisa mengalihkan pandang padanya—selalu saja perlente.
“Hey, bagaimana
kabarmu?”
“Ya, seperti
yang kau lihat,” jawabnya sembari menarik kursi, dan duduk di hadapanku.
Sekitar lima
belas menit kami berbasa-basi: saling menanyakan kabar dan kesibukan. Setelah
lima belas menit yang membosankan itu, ia pun mulai mengubah air mukanya. Ia
memang nampak sedang memenjarakan sesuatu dalam kepalanya, dalam hatinya. Hal
itu bisa kulihat dari bola matanya. Matanya tajam, tidak seperti mata-mata yang
sering kutemui di kampusku: mata-mata yang kosong dan polos, seolah tidak ada
sesuatu apapun dalam batok kepalanya. Ya, seperti mata seorang dungu. Nah,
kawanku yang satu ini boleh dikatakan sebagai antitesis dari kebanyakan
mata-mata yang dungu itu.
“Akhir-akhir
ini aku merasa semakin muak dengan cerita-cerita di kampus kita ini.” Ia
memulai dengan keseriusan.
“Cerita-cerita
apa yang kau maksud?” Tanyaku penasaran.
Ia terlihat
sedang menimbang-nimbang, lantas, “Baiklah, akan kuceritakan padamu beberapa
cerita yang memuakkan, yang terjadi di kampus kita ini. Barangkali suatu saat
kau bisa menuliskan cerita ini untuk banyak orang, agar mereka semua mengerti
keadaan sebenarnya kampus ini.”
Ia berbicara
dengan wajah mengarah ke meja. Dan, aku akan mencoba menjadi seorang pendengar
yang baik. Karena, ia pun berharap aku dapat menceritakan ceritanya pada orang
lain, namun lewat tulisan. Maka dari itu, aku mesti menyimaknya baik-baik agar
aku nantinya tidak keliru memahami ceritanya, sehingga cerita itu bisa sampai
pada orang lain dengan baik.
“Soal dosen
yang mengajar di kampus kita, kau tahu, apa yang sudah kudapat dari perkuliahan
selama beberapa semester ini? Jawabannya, nihil. Ya, aku tidak banyak
mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari ruang kelas. Akhirnya, kini aku
benar-benar bosan dan muak dengan perkuliahan. Kau tahu salah satu
penyebabnya?” Ia menanyaiku, dan tidak memperdulikan jawabanku, “Dosen, atau
pengajar. Ya, itu. Selama beberapa semester ini, banyak kutemui dosen
abal-abal. Dosen yang kurang bahkan tidak kredibel, tidak kompeten, tidak
kompetitif, dan tidak profesional. Aku tahu pikiranmu, kita tidak bisa
serta-merta menyalahkan dosen begitu saja, ‘kan? Aku tahu, kita tidak bisa
menggantungkan semuanya pada dosen. Aku juga tahu, kita sudah bukan siswa lagi,
kita sudah maha-nya siswa. Kita mesti mandiri. Kita mesti ini, mesti itu, dan
bla-bla-bla. Shit! Aku tahu semua
itu. Tapi, jika kau melihat polah dosen yang tidak mengerti cara mengajar,
hanya membaca ulang apa yang terpantul dari proyektor. Atau, dosen yang
senangnya datang terlambat, seenak perutnya sendiri, tidak disiplin. Atau juga
dosen yang tidak menyiapkan dan memahami materi perkuliahan yang diajarkannya
sendiri, dan akhirnya kebingungan dengan apa yang akan disampaikannya. Nah, apakah
dosen-dosen semacam itu masih patut kita maklumi? Apakah dosen seperti itu
masih pantas untuk tidak kita sebut sebagai dosen abal-abal? Hah?”
Aku diberondong
pertanyaan, dan aku lagi-lagi harus menganggukan kepala, karena aku pun
mengalami hal seperti apa yang dialaminya. Aku pernah diajar oleh salah satu
dosen yang ciri-cirinya seperti yang telah dijabarkan oleh kawanku ini. Dosen
itu seperti tidak mengerti apa yang diajarkannya, tidak paham apa yang
dibicarakannya. Sayangnya, kawanku ini tidak menyebutkan nama dosennya. Dan,
aku pun tidak menanyakannya lantaran aku segan untuk memotong pembicaraannya.
Mungkin, dosen itu adalah dosen yang sama, mengajar kami berdua di kelas yang
berbeda. Atau mungkin di kampus ini memang banyak dosen yang seperti itu?
Entahlah. Aku tidak akan menyimpulkannya saat ini, karena aku perlu bukti. Dan,
kawanku ini masih dengan ceritanya. Siapa tahu, aku dapat menarik kesimpulan
ketika ia mengakhiri ceritanya.
“Aku heran
dengan kampus kita ini, juga mahasiswanya. Aku heran dengan tindak-tanduk
mahasiswa kita yang hanya berorientasi dengan sertifikat. Ya, aku banyak
mendengar minat teman-temanku mengikuti seminar atau workshop yang di adakan di
kampus kita. Kau tahu apa kata teman-temanku itu?”
Kali ini ia
mengambil jeda agak lama. Mungkin, kali ini ia betul-betul mengharap jawabanku.
Namun, perkiraanku ternyata keliru. Setelah ia menyeruput kopi dan menghisap
Dji Sam Soe-nya, lalu ia melanjutkan kegeramannya,
“Minat
teman-temanku begitu seragam. Ya, hampir seragam. Hampir semua temanku
berpendapat, bahwa mereka mengikuti seminar dan workshop hanya untuk
mendapatkan sertifikat, yang berkaitan dengan poinisasi. Coba pikir, hanya
untuk sertifikat. Hanya demi poin. Selain tingkah mahasiswa kita yang menjadi
penjilat sertifikat, banyak juga kutemui mahasiswa kita yang bungkam atas
permasalahan di sekitarnya. Mahasiswa sekarang terlalu apatis, bahkan seperti bocah
autis. Lihat saja, apakah mahasiswa kita suka berdemo? Tidak, bukan? Mahasiswa
kita sekarang seperti tidak memiliki daya kritis. Otak mereka tumpul.
Barangkali gara-gara terlena dengan gadget di tangannya.”
“Ya, ya, aku
sudah lama sekali tidak melihat mahasiswa kita melakukan demonstrasi,” kali ini
ia membiarkanku mengeluarkan suara.
“Kau masih
ingat kan dengan kata-kata bahwa, mahasiswa adalah agent of change? Ya, kau pasti hafal dengan kalimat itu. Aku rasa,
di kampus kita kalimat itu sudah musnah. Padahal dengan melihat jumlah
organisasi di kampus kita ini, seharusnya ada banyak pula mahasiswa yang
memiliki daya kritis terhadap kondisi di sekitarnya. Namun apa? Tiap organisasi
sepertinya hanya menimbun anggota, hanya memperhitungkan kuantitas, bukan
kualitas.
“Sekarang kau
sudah tahu. Begitulah keadaannnya. Ya, kalau tahu begini persoalannya, aku
kira, aku tidak sampai hati untuk kuliah. Ya, aku tidak perlu menjadi
mahasiswa, apalagi seperti mahasiswa yang kerjaannya cuma: kuliah, pulang,
tidur, makan, mandi, menggarap tugas, tidur lagi, dan kuliah lagi. Terus dan
terus seperti itu. Aku heran, apa mereka tidak merasa bosan dengan rutinitas
semacam itu? Ah, aku pun telah bosan bicara terus. Untuk saat ini, mungkin itu
saja yang perlu kuceritakan padamu. Terimakasih telah mendengarkanku.”
Purwokerto, 2014



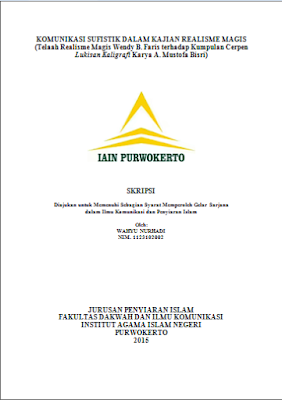
Comments