Redupnya Cahaya di Wajah Nurlaela*
oleh
Wahyu Noerhadi
Dengan amarah yang berkobar, mata golok siap menyambar. Urat leher siap jadi
sasaran. Jerit orang-orang pun membuat suasana kian menegangkan.
***
Perempuan berlesung pipit, bermata sipit, berambut ikal, dan bertubuh
langsing itu adalah bibiku dari jalur ibu. Namanya Nurlaela. Mungkin maksudnya
Nurlaila, yang dalam Bahasa Arab artinya cahaya malam. Namun, sepertinya, orang
Sunda memang sudah terbiasa melafalkan “ai” menjadi “ae”. Ya, seolah-olah telah
meniadakan hukum mad liin dalam ilmu tajwid. Seperti juga, orang Sunda
kerap mengubah pengucapan kata atau kalimat yang mengandung huruf “f” menjadi
huruf (hurup?) “p”. Tetapi, itu hanyalah masalah atau kebiasaan lidah.
Bagaimana pun pengucapannya, mungkin maksud hati tidaklah lain. Buktinya,
bibiku itu memang memiliki cahaya di wajahnya.
Nurlaela adalah anak bontot dari empat bersaudara. Dan, sejak umur 12
tahun ia sudah diitinggalkan kedua orang tuanya. Maka, sejak saat itu
kebutuhannya ditanggung oleh Ayah dan kedua pamanku. Ade, panggilannya di
keluarga, merampungkan pendidikannya hanya sampai pada SMA lantas menggantungkan
hidup seperti jamaknya orang-orang di desaku: menjadi buruh pabrik di kawasan
industri di belakang desa. Hampir, hampir setiap manusia di desaku lahir,
tumbuh, dan beranak-pinak di situ-situ juga. Setiap kepala keluarganya memiliki
profesi yang serupa, yakni buruh pabrik. Karena, di desaku, dengan hanya
bermodal KTP dan ijazah SD, tiap orang bisa menjadi buruh di kawasan industri. Dan,
pamanku, Mang Udin—seorang yang memiliki ijazah S1—juga pada akhirnya berprofesi
sebagai satpam di salah satu pabrik di kawasan industri itu.
Sungguh, keadaan di tanah tempat kelahiranku kini telah berubah
sedemikian rupa. Misalnya, dulu, jarak antara satu rumah dan rumah lainnya
sekurang-kurangnya 10 meter. Kini, jarak itu benar-benar menciut menjadi
hitungan satu-dua jengkal saja. Bagaimana tidak, tiap orang berlomba-lomba
membangun kontrakan untuk ditempati para pendatang. Keadaan pun semakin
berjubel dengan melihat jumlah pendatang yang akhirnya betah dan lebih memilih
hidup di tempat yang sudah padat itu. Ditambah muda-mudi yang menikah dengan
tetangganya sendiri; berkeluarga dan membesarkan anak di situ-itu juga. Setelah
anak-anaknya dianggap mampu bekerja dan memiliki ijazah SD, lantas anak-anak
itu pun masuk pabrik di belakang desa. Selanjutnya, mereka pun akan mengikuti
jejak para orang tuanya: lahir, tumbuh, berkeluarga, dan membesarkan anaknya
untuk menjadi buruh pabrik. Seakan-akan setiap anak yang lahir di desa itu
memiliki nasib yang serupa: menjadi buruh pabrik. Dan, anak-anak itu kelak akan
menularkan nasibnya pada anak-anaknya pula.
Sepertinya, sampai 100 tahun kemudian, kehidupan akan terus berputar
seperti itu. Hingga akhirnya, mungkin, seluruh pabrik itu terbakar dan gulung
tikar. Sungguh, saat ini, pabrik-pabrik terus tumbuh dan berkembang pesat.
Beriringan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di desaku. Ya, penduduk pribumi
di desaku seperti kedatangan penjajah. Namun, bedanya, kedatangan penjajah di
desaku itu disambut dan dirayakan dengan penuh kegembiraan.
Ah, maaf, aku malah melantur kesana-kemari. Padahal, aku hanya hendak
menuturkan cerita tentang bibiku, Nurlaela. Kini, ia telah mempunyai anak: empat,
dan laki-laki semua. Ia menikah setelah beberapa bulan pacaran dengan Mang
Wawan: seorang buruh pabrik dari desa tetangga. Ya, Mang Wawan adalah pria yang
beruntung. Ia dapat dengan leluasa menyentuh cahaya si bunga desa. Dan, akhirnya
Wawan pulalah yang meredupkan cahaya di wajah Nurlaela.
Mang Wawan, Pria berambut keriting dan berperawakan jangkung itu sebenarnya
paman yang menyenangkan. Ia sering mengantarku ke sekolah waktu SMP dan
mengajakku jalan-jalan. Ia juga pria yang ramah dan suka membantu keluarga.
Misalnya, ia rajin mengurusi pembayaran pajak sepeda motor ayahku dan Mang
Udin. Ia memang paham betul mengurusi hal semacam itu.
Ya, Mang Wawan memang paman yang baik. Namun, pernah ada kabar yang
kurang mengenakkan tentang perilakunya ketika ia masih bujang. Dan, kabar itu
sempat menggoyahkan kepercayaan Ibu, Ayah, dan kedua pamanku untuk merestui pernikahan
Bibi Ade dengannya. Namun, kabar itu hanya sembarang kabar. Dan, pernikahan
tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Setelah beberapa tahun, aku dengar, kondisi keluarga Mang Wawan dan Bibi
Ade mulai berubah. Mang Wawan dianggap terlalu banyak tingkah. Dan, ayahku
selalu bersikap tenang dan menganggap seolah semuanya baik-baik saja. Beda lagi
dengan Mang Udin. Ia selalu melemparkan senyum menyeringai ketika melihat Mang
Wawan. Mungkin, sejauh cerita yang kudengar, Mang Udin merasa sakit hati atas
pertolongan yang telah ditawarkannya kepada Mang Wawan, ketika adik iparnya itu
tengah lontang-lantung lantaran dikeluarkan dari tempat kerjanya. Entah karena
apa, pada hari ke-5 ia masuk kerja di pabrik tempat Mang Udin juga bekerja,
Mang Wawan kembali diberhentikan dari pekerjaannya. Mungkin itu yang membuat
Mang Udin selalu memiliki kecurigaan terhadap tindak-tanduk adik iparnya itu.
Lebih-lebih, ketika mendengar bahwa BPKB mobil Mang Asep—anak ketiga setelah
Mang Udin—digadaikan oleh Mang Wawan untuk keperluan entah apa. Juga ketika
Mang Udin mendengar keluhan Bibi Ade soal pihak bank yang datang menagih utang
Mang Wawan. Semua kabar itu membuat Mang Udin makin geram.
“Sudah, De. Tinggalkan saja si Wawan itu. Cari laki-laki lain yang mampu
menghidupimu,” kata Mang Udin, ketika aku dan pamanku itu mengunjungi Bibi Ade
di kontrakan, tempat tinggalnya bersama Mang Wawan dan keempat anaknya. Bibi
Ade yang kurus kering, tengah menyuapi kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Sedang
kedua anaknya yang lain, yang duduk di bangku kelas 1 dan 3 SD, tengah berebut remote
control televisi. Dan, Mang Wawan memang sedang tidak di tempat.
“Tapi, Kang...”
Ya, Bibi Ade sepertinya tidak akan pernah mengindahkan saran kakaknya
itu. Bibiku sudah kadung cinta, apa mau dikata. Katanya, Bibiku selalu berdoa
agar suaminya mendapat kerja dan betah menjadi buruh pabrik. Namun, Mang Wawan
sampai saat ini belum menerima atau menjemput doa istrinya itu. Ia masih saja
mondar-mandir mengharap upah atas kerjanya mengurusi pembayaran pajak sepeda
motor, dan kerja serabutan lainnya.
Mang Wawan menghidupi istri dan keempat anaknya hanya dengan upah yang
tak seberapa. Pernah suatu waktu, ayahku menawari pekerjaan pada Mang Wawan
untuk jadi tukang sampah di kawasan industri dengan gaji yang lumayan. Tapi,
Mang Wawan menolak halus tawaran itu dan tetap memilih berkeluyuran ke tempat
teman-temannya. Hingga akhirnya, Mang Wawan jadi jarang pulang, sampai satu-dua
minggu bahkan satu bulan. Mendengar semua itu, Mang Udin semakin berang.
“Wan, kamu teh kenapa sih? Enggak kasihan sama anak-istri? Kamu
pikir, kamu teh masih bujang, senangnya keluyuran. Kamu teh punya
anak-istri yang kudu dinafkahi!”
Mang Udin geram, dan menggebrak pintu yang sudah terbuka. Ketika itu,
Mang Wawan, Bibi Ade, dan keempat anaknya sedang ada di rumahku. Dan, tiap sore
Mang Udin memang selalu mampir ke rumahku.
“Kalau aku enggak kasihan sama si Ade, udah kuhajar mukamu itu Wan! Kamu
lihat,” lanjut Mang Udin seraya menunjuk ke arah Bibi Ade dengan dagunya,
“istri kurus kering, anak enggak keurus. Apa kelakuanmu bakal seperti itu
terus?”
Melihat kemarahan Mang Udin, aku sedikit merinding. Mang Wawan diam
ketakutan. Sedangkan bibiku dan anaknya yang kecil-kecil menjerit-jerit serta
menanggis histeris. Bagaimana tidak, Mang Udin bicara dengan mengacungkan
pentungan.
“Dari awal, aku memang tidak merestui hubunganmu dengan si Ade. Aku sama
sekali tidak merestui pernikahanmu dengan adikku. Aku tahu, jodoh itu urusan
Allah. Tapi aku sebenarnya tidak setuju jika adikku harus hidup dan berkeluarga
denganmu. Jika kamu sudah tidak mampu lagi memberinya nafkah, ceraikan saja
adikku!”
Pentungan yang digenggam Mang Udin hampir mendarat di kepala Mang Wawan jika
saja ayahku tidak mampu menahan dan menarik tubuh adiknya itu.
“Sudah, Din. Enggak enak sama tetangga.” Ujar ayahku menenangkan suasana.
Namun, bibiku dan anak-anaknya masih saja menjerit dan menangis. Dan, para
tetangga memang menyaksikan kejadian itu.
Setelah lima belas menit berselang dan api di dada Mang Udin padam,
keadaan mulai tenang. Bibiku dan anak-anaknya hanya menangis sesenggukan. Para
tetangga pun masuk kembali ke dalam rumahnya, dengan raut muka yang seolah tak
terjadi apa-apa. Tapi, aku tahu, di dalam rumah, mereka akan
memperbincangkannya. Mang Udin pun hendak pulang ke rumahnya.
“Awas kamu Wawan kalau sampai benar-benar menyakiti hati si Ade!”
Mang Udin kembali mengingatkan, dengan mengacungkan pentungan ke arahnya
Mang Wawan. Lantas, Mang Udin berlalu menunggangi sepeda motornya. Mang Wawan,
Bibi Ade, dan keempat anaknya juga kembali ke kontrakannya. Sebelum mereka
pulang, ayahku berpesan:
“Wan, maafkan kelakuan Kang Udin tadi. Mungkin, dia kecapaian. Dia hanya
kasihan melihat kamu dan keluargamu. Carilah pekerjaan, Wan!”
“Iya, Kang,” ucap Mang Wawan.
Beberapa bulan setelah peristiwa itu, aku dengar kabar bahwa kehidupan
Mang Wawan dan keluarganya masih seperti itu-itu juga. Bahkan, mereka hendak
diusir oleh si empunya kontrakan, lantaran selama setengah tahun belum bayar
sewa kontrakan. Namun, Mang Udin dan Mang Asep keburu membayarnya. Juga
sangkutan Mang Wawan dengan bank, telah diatasi mereka berdua.
Aku juga dengar kabar, anaknya Bibi Ade yang paling kecil sering sekali
sakit-sakitan. Anaknya yang kedua, yang masih kelas 1 SD, sudah tidak mau
sekolah lagi karena tidak pernah diberi uang jajan. Mang Wawan pun tambah
jarang pulang, bisa sampai satu setengah bulan ia tidak pulang. Dan, ketika
Bibi Ade melahirkan putra yang kelima, Mang Wawan masih belum juga pulang. Tiap
kali kami berkunjung ke kontrakan, kami memang tidak pernah sekali pun melihatnya.
Suatu kali, Ayah dan Ibuku bertanya kepada orang tua Mang Wawan. Dan, orang
tuanya pun tidak mengetahui keberadaan Mang Wawan.
***
Sore hari di bulan Juli, langit begitu sengit. Mata petir dan aroma tanah
merah yang basah menguap dan mengabarkan kepiluan. Di beranda, aku memandangi
hujan. Dan, dari kejauhan kulihat Bibi Ade tengah berjalan tergopoh-gopoh ke
arah rumahku. Dengan air muka yang tak kumengerti, Bibi Ade melewatiku begitu
saja dan langsung masuk ke rumah. Aku heran dan hanya mampu mengikuti geraknya
dengan mata.
“Teteh, si Wawan nikah lagi. Tadi Ade lihat si Wawan dengan perempuan
lain sedang berpelukan di kamar, di rumah orang tua si Wawan.” Ucap Bi Ade sambil
menangis di pelukkan ibuku.
“Astagfirullah, yang benar De?”
“Iya, Teh. si Wawan dan orang tuanya sendiri yang bilang ke Ade kalau
mereka memang sudah menikah dua bulan yang lalu.”
Ibuku pun akhirnya menangis sembari mengelus-ngelus rambut Bibi Ade yang
basah. Mendengar itu, ayahku cepat saja menghubungi Mang Udin, untuk mendatangi
Mang Wawan di rumah orang tuanya. Setelah menunggu 10 menit, Mang Udin pun
tiba. Tanpa kata, Ayah dan Mang Udin langsung pergi. Sayangnya, ayahku tidak
mengetahui bahwa Mang Udin telah menyelipkan golok di balik jaketnya.
Bogor,
2012 – Tanjungpinang, 2014
*Termaktub dalam antologi cerpen Misteri Jodoh
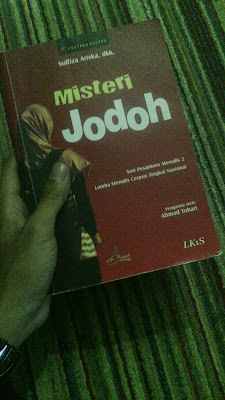



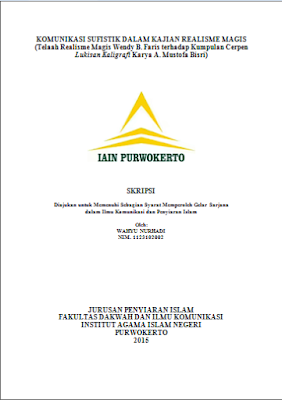
Comments