Rahasia Lusi*
Pada Jumat malam, di minggu
ketiga bulan Mei, ia belum juga mampu menekan satu tombol pun di keyboard
komputernya. Sampai beberapa menit, halaman di layar komputer itu masih cukup bersih.
Di halaman itu hanya ada satu nama, yang mungkin akan dijadikan sebagai judul karangannya: LUSI.
***
Lusi tiba di rumahnya sore hari.
Biasanya ia tak pernah pulang terlambat. Lambat-lambatnya jam satu siang sudah
tiba di rumah. Tapi, di sepanjang jalan dari sekolah ke rumahnya yang berjarak
sekitar 500 meter, ia diikuti oleh seorang lelaki yang tak ia kenal. Makanya ia
memilih jalan memutar untuk sampai ke rumahnya, dengan maksud mengecoh lelaki
itu. Ia terus berjalan menunduk. Setibanya di depan rumah, sekilas ia melirik ke
belakang. Dan, lelaki itu melemparkan senyum padanya. Cepat-cepat Lusi membuka
lantas membanting pintu rumahnya dengan keras. Sampai-sampai lelaki itu pun kaget.
Esoknya, ketika Lusi hendak
berangkat sekolah, lelaki itu sudah berdiri di seberang jalan. Lusi menatap
tajam mata lelaki itu. Lelaki itu kembali tersenyum padanya. Wajah Lusi tampak
ketakutan. Ia berjalan setengah berlari, dan lelaki itu masih membuntuti.
Sesampainya di gerbang sekolah, Lusi berhenti dan memberanikan diri,
“Paman mau apa? Kenapa Paman
mengikutiku terus?” Ucap Lusi dengan bibir sedikit bergetar.
“Jangan takut, Paman hanya ingin
menngenalmu.
Paman tidak akan berbuat jahat,” jawab Lelaki itu dan mendekat ke arah Lusi.
Lusi melangkah mundur. Satu-dua
siswa melewati gerbang sambil memandanginya. Kemudian, Lusi memasuki
gerbang dan meninggalkan lelaki itu. Lusi tampak kesal padanya. Di jam
istirahat, Lusi pun tidak meninggalkan kelas. Ia mungkin mengira kalau-kalau
lelaki itu masih ada di luar gerbang.
“Pagi tadi kau bicara dengan
siapa?” Tanya seorang kawan di meja sebelahnya.
“Hoo,” ia terkejut
mendengar suara kawannya, “Bukan siapa-siapa.” Jawabnya.
Bel pulang sekolah pun berbunyi.
Anak-anak kelas 1, 2, dan 3 berhamburan dari kelasnya masing-masing. Ada yang
segera menyerbu jajanan, ada yang beli mainan, dan ada juga yang langsung
pulang. Satu setengah jam kemudian, bel berbunyi lagi. Anak-anak kelas 4, 5,
dan 6 keluar dengan lebih tertib. Di luar gerbang, lelaki itu mencari-cari
seseorang. Ketika Lusi terlihat sedang berjalan menuju gerbang, Lelaki itu pun
tersenyum. Lusi berjalan paling belakang, menunduk, dan selalu sendirian.
“Adik Paman juga kelas lima.
Sama kayak Lusi,” lelaki itu membarengi langkah Lusi, “Lusi masih takut pada
Paman? Baiklah, jika Paman berbuat macam-macam, Lusi boleh laporkan Paman pada
ayah Lusi, atau ke ibu guru. Atau, bapak polisi itu.” Lelaki itu mengarahkan
telunjuknya ke seorang polisi yang sedang mengatur lalu lintas.
“Aku tidak suka melapor.” Lusi menjawabnya
dengan sedikit ketus, “Tapi aku akan berteriak jika Paman membuatku takut.”
“Berarti sekarang Lusi sudah
tidak takut?”
Lusi tidak menjawabnya. Lusi
menghentikan langkahnya kemudian menatap wajah lelaki itu dengan berani. Lelaki
itu lagi-lagi tersenyum, dan sepertinya senang mengetahui bahwa Lusi sudah
tidak takut lagi kepadanya.
“Lusi mirip sekali dengan adik
Paman.”
“Apakah dia aneh juga?”
“Aneh? Aneh bagaimana?” Lelaki
itu terlihat heran.
Mereka berdua telah sampai di
depan rumah Lusi. Rumah yang warna biru lautnya itu sedikit pudar dan
mengelupas di beberapa tempat. Terutama di tembok bagian kanan. Bagian itu memang
selalu terkena sinar matahari tiap sorenya. Dan pohon-pohon pun, seperti pohon mangga
dan jambu biji hanya ada di sebelah kiri rumah. Jadi, tidak bisa barang sedikit
meneduhi tembok sebelah kanan, yang akhirnya dipenuhi coretan-coretan dari
krayon. Coretan itu bergaris-garis dan berwarna-warni. Persis seperti labirin.
“Sepertinya, Paman memang tidak
jahat. Paman mau masuk?”
“Ya, boleh.”
“Kebetulan, ayahku juga sedang tidak
di rumah,” Lusi berkata sambil mendorong pintu yang terlihat berat itu.
“Ke mana memang?”
“Aku tidak perlu tahu dia ke
mana, dan aku juga tidak suka dia di rumah.”
“Lusi tak boleh begitu pada Ayah.”
“Dia juga harusnya tak boleh
memukuliku.”
***
Suatu malam, seperti juga malam-malam
sebelumnya, Lusi begitu kedinginan. Tubuhnya meringkuk dan terbungkus rapi oleh
selimut. Ia juga mengenakan sarung tangan dan sepatu bot milik ayahnya.
Berkali-kali ia menguap tapi matanya tetap saja terbuka, menatap lampu di
langit-langit kamarnya. Ya, sepanjang malam, ia tak pernah mematikan lampu
kamarnya. Dan ibunya pun pernah berpesan, “Jika kau merasa takut, maka jangan
pernah matikan lampu kamarmu.” Ibunya berkata sambil mengelus rambut Lusi yang
ikal dan panjang.
Malam itu gigi-gigi Lusi
bergemelutuk, dan wajahnya tampak begitu ketakutan. Ketika ia hendak menarik
selimut untuk menutupi wajahnya, tiba-tiba saja ia berteriak,
“Aaaaaaa... Jangan,
jangan bawa aku,” tubuhnya bergerak ke sana-sini, “Tidak, tidak... Aku tidak
mau pergi denganmu.”
Daaar... Ayah Lusi mendobrak
kamar, “Hey... Diam! Ini sudah tengah malam,” ayahnya memelototi dan tangannya
sudah mencengkeram mulut Lusi, “Kalau kau tak bisa diam nanti kurobek mulutmu.
Mengerti kau?”
Lusi hanya mengangguk-angguk.
Matanya berkaca-kaca.
“Dasar, anak aneh!” Pungkas
ayahnya setelah mengeplak kepala Lusi.
Setelah malam itu, setelah
ibunya tiada dan ayahnya makin rajin memukulinya, ia tak pernah lagi berteriak.
Ketika ketakutan, Lusi akan langsung menjejali mulutnya dengan selimut, atau ia
akan menggigit tangannya sendiri.
***
Hari-hari berikutnya, tiap pagi
hingga sore, mereka selalu bersama. Kecuali jika Lusi berada di ruang kelas
atau di kamar mandi. Lusi dan lelaki itu memang terlihat makin akrab. “Sekarang
adik Paman ada di mana? Paman tak pernah menemuinya?” Lusi mengawali
perbincangan.
Lelaki itu tak langsung
menjawab. Ia melihat wajah Lusi, “Sejak kecelakaan itu, Paman tak pernah lagi
melihatnya. Waktu itu, dia masih kelas lima. Sama seperti Lusi sekarang. Dia
juga cantik, seperti Lusi. Adik paman bercita-cita menjadi seorang pilot.
Katanya, dia ingin mengajak Paman berkemah di bulan. Sebab, katanya, bumi ini
panas. Dan dia memang sering merasa kepanasan. Kalau tidur dia tak pernah mau
mengenakan baju. Apalagi selimut. Dia hanya ingin memakai kaos dalam. Di
sekolah, dia pintar dan punya banyak teman. Lusi juga punya banyak teman ‘kan?”
Lelaki itu meminta jawaban pada Lusi yang malah diam dan menunduk.
Lelaki itu pun melanjutkan, “Paman
masih ingat permintaan terakhirnya. Dia minta Paman menuliskan serta membacakan
cerita tentangnya. Dan sampai sekarang Paman tidak bisa membacakan cerita itu pada
adik Paman, meski ceritanya sudah selesai Paman tuliskan. Sore itu, waktu Paman
berlibur bersama ayah, ibu juga adik Paman, Tuhan mengambilnya terlebih
dahulu,” Lelaki itu mengelap air di sudut matanya. Lama ia mengambil jeda,
“Kini Adik, Ayah dan Ibu Paman mungkin berada di surga.”
“Diam, Paman. Kita jangan
bergerak dan pura-pura tidak melihat mereka,” tiba-tiba Lusi menghentikan
langkahnya dan langkah lelaki itu.
“Mereka siapa, Lusi?” Wajah
lelaki itu kebingungan.
Lusi memandangi lelaki itu dan meletakkan
telunjuknya di bibir. Mereka pun mematung di depan bangunan tua. Setelah
sekitar 15 menit mereka berdiam diri, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan.
“Paman mampir, ‘kan? Aku ingin menceritakan
rahasiaku pada Paman. Kuharap Paman mau mendengarkan. Mungkin suatu saat Paman
bisa menuliskannya.”
Sore itu, ayah Lusi memang
sedang tidak di rumah. Bibi pembantu pun sudah pulang. Ibunya,
sudah meninggal.
Di luar langit gelap, dan gerimis pun berjatuhan. Dua burung yang nangkring di
kabel listrik akhirnya terbang, kembali ke sarang.
Di atas sofa coklat itu mereka
duduk. Dan Lusi mulai bercerita,
“Paman tahu, aku bisa melihat
hantu-hantu?” Lusi menoleh ke arah lelaki itu. Dan, tanpa menghiraukan
keheranan lelaki itu, Lusi melanjutkan, “Mereka, yang tadi kulihat di gedung
tua itu adalah hantu-hantu penasaran. Mereka minta pertolongan. Tapi, melihat
wajahnya saja aku tidak berani, mana mungkin aku menolong mereka. Di daerah
tempat nenekku tinggal, aku juga pernah menjumpai hantu-hantu yang sangat
mengerikan. Hantu-hantu itu berteriak-teriak minta tolong. Hantu-hantu itu mengatakan
bahwa mereka dibunuh oleh saudaranya sendiri. Kebanyakan dari mereka dibunuh
dengan cara disembelih. Kemudian, orang-orang menguliti dan membuang mayatnya
ke sungai. Mereka dibunuh pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima,”
“Dari mana Lusi tahu cerita
itu?” Tanya lelaki itu heran.
“Para hantu sering bercerita kepadaku,
Paman. Makanya, aku tahu semua hal yang tidak diketahui orang-orang dewasa. Dan
orang dewasa pun kadang tidak tahu apa-apa. Aku tidak suka menjadi dewasa,” Wajah
Lusi tampak kesal, kemudian menunduk, “Tapi, gara-gara aku sering bicara dengan
hantu-hantu, semua orang menganggapku aneh. Teman-teman di sekolah, juga ibu
guruku memanggilku ‘bocah aneh’. Karena mereka pikir, aku sering bicara
sendiri. Oh, apakah Paman tahu kalau hantu-hantu ternyata tidak bisa melihat
satu sama lain? Kata salah satu hantu yang ada di rumah ini, para hantu melihat
apa yang ingin mereka lihat,” Lusi menahan ceritanya dan lelaki itu terkejut.
“Benarkah Lusi?”
“Paman juga harus tahu, hantu-hantu
kebanyakan tidak sadar kalau dirinya sudah mati.”
***
Pada Jumat malam, di minggu
ketiga bulan Mei, ia belum juga mampu menekan satu tombol pun di keyboard
komputernya. Sampai beberapa menit, halaman di layar komputer itu masih cukup
bersih. Di halaman itu hanya ada satu nama, yang mungkin akan dijadikan sebagai
judul tulisannya: LUSI. Setelah beberapa menit itu, tiba-tiba kepalanya begitu
pening. Lelaki itu teringat pada perkataan terakhir Lusi sore itu. Lelaki itu tersungkur
dan sadar bahwa dalam kecelakaan itu ia juga ikut mati bersama ayah, ibu, dan
adiknya.
Purwokerto, 2015
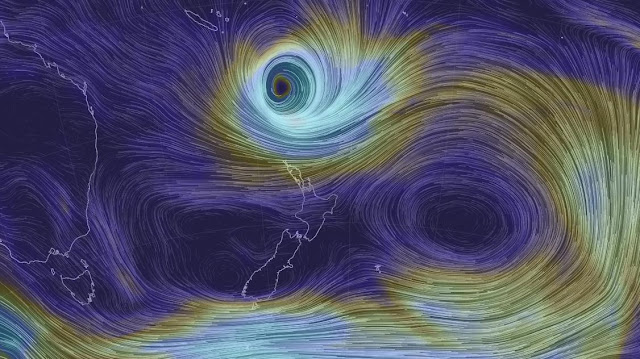



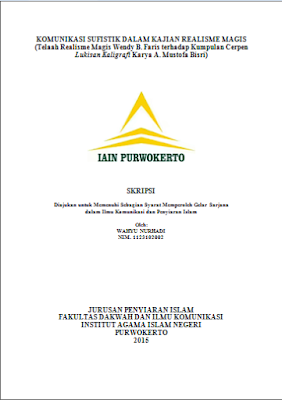
Comments