Memprotes Realitas*
Oleh: Wahyu Noerhadi
Yang macet di tengah lika-liku peradaban
Tak kunjung membaik juga
R.I.P. untukmu: Indonesia
- M. Rifky Fathur Rizqi -
Perlu
saya sampaikan di awal bahwa, buku ini menghadirkan pelbagai wacana yang dikemas
dengan apik oleh mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) STAIN Purwokerto
angkatan 2012. Wacana itu dikemas dalam bentuk puisi, cerpen, esai, dan karya
tulis ilmiah. Tentu, saya sedikit kewalahan untuk menemukan benang merah dari
apa yang mereka sampaikan dalam karyanya. Lantaran saya mesti mondar-mandir dari
satu karya ke karya yang lain dalam bentuk yang berbeda, misal dari karya puisi
ke karya tulis ilmiah. Namun kita tahu, setiap karya (naskah) diciptakan dengan
menggunakan bahasa (baca: tulisan). Kemudian, dengan bersandar pula pada
pendapat Sutan Takdir Alisjahbana (Wachid dan Heru, 2011: 5) bahwa bahasa
adalah manifestasi atau alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan
seseorang. Maka, wajar saja jika pada akhirnya saya yakin untuk dapat menemukan
suatu keseragaman yang menjadi perbincangan mahasiswa KPI 2012 dalam buku ini.
Sebab, ada bahasa yang membantu saya untuk dapat memahami—atau setidaknya
menebak-nebak—apa yang mereka bicarakan.
Mari
kita barang sedikit mencermati pembicaraan mereka. Di awal-awal, saya langsung
menemukan adanya keseragaman pada karya puisi mereka. Mereka secara serempak mengungkapkan
rasa syukurnya pada Tuhan; mereka memuji keagungan Tuhan; mereka berjamaah
memanjatkan doa-doa pada Sang Kuasa. Dan, cara mereka melukiskan perasaan serta
pikirannya pun hampir serupa. Padahal, Sapardi Djoko Damono pernah mengatakan
bahwa, kiasan atau majas akan berbau sengit jika terlalu banyak yang
mengucapkan. Ungkapan klise bahkan dianggap sebagai sesuatu yang haram jika
dipakai oleh penyair. Namun, saya berkeyakinan bahwa mereka memang tidak sadar
menghadirkan keseragaman itu. Saya pikir, memang itulah isi kepala dan hati
mereka. Sehingga, muncullah ungkapan yang serupa.
Dari
karya puisi teman-teman KPI 2012, saya menjumut puisi-puisi yang berbeda dari
tema puisi pada umumnya dalam buku ini. Dan, bait terakhir puisi milik M. Rifky
Fathur Rizqi yang berjudul “Menuju Senja” di atas itu, sengaja saya kutipkan sebagai
contoh tema yang juga dibangun oleh teman-temannya dalam karya cerpen, esai,
dan karya tulis ilmiah. Jadi, ada semacam keseragaman lain yang meliputi
seluruh bentuk karya, selain keseragaman yang kita jumpai dalam bentuk karya
puisi.
Rifky, dalam puisinya itu, coba menyuarakan
kejemuannya pada bangsa ini. Mungkin Rifky teramat kesal dengan realitas yang tengah
melanda bangsa Indonesia. Hal itu
nampak ketika di baris akhir puisinya ia mengatakan, ‘R.I.P. untukmu:
Indonesia’. Lagi, Rifky menuliskan kejemuannya lewat puisi yang ia beri
judul “Ejekan Batu Cadas”. Rifky mengatakan, ‘Aku memang indah/ Tetapi
kenapa aku tetap tertindas?//’ (bait pertama, baris tiga dan empat). Saya
kira, aku-lirik itu adalah ‘jelmaan’ dari batu cadas. Batu cadas bersuara lewat
Rifky. Atau sebaliknya, Rifky sengaja mendengarkan keluh-kesah batu cadas untuk
kemudian ia puisikan. Keduanya sama saja: memprotes keadaan.
Setali
tiga uang, puisi sosial disampaikan pula oleh Juli Ibnu Alkamzy yang bertajuk
“Gadis Bermata Sayu”. Juli menuliskan, ‘...Aku melewatimu dengan ta’zim/
Inginku mengelus kumal rambutmu/ Kutinggalkan beberapa rupiah dalam mangkuk
kusammu/ mayat-mayat hidup terus melewati sayu matamu dengan/ rupiah dan
rupiah/’. Ada pemandangan yang ingin dilukiskan oleh Juli dalam puisinya
itu. Pemandangan yang acap kali kita jumpai di persimpangan-persimpangan jalan.
Tentu, kita mafhum bahwasanya seseorang (penyair) yang hendak menuliskan puisi
dituntut untuk peka dalam memandang sesuatu. Dan, kepekaan itupun dimiliki oleh
Juli. Saya pikir, apa yang disampaikan oleh Juli dalam puisinya itu dapat
menjadi bahan refleksi kita untuk selalu berbagi pada sesama, misal pada
pengemis. Karena, tentu kita tak ingin disebut sebagai ‘mayat-mayat hidup’ yang
acuh tak acuh pada mereka.
Selanjutnya,
pada karya cerpen, mula-mula saya langsung dihadapkan dengan kisah-kisah merah
jambu yang mereka tuturkan. Kisah-kisah cinta yang kerap dibalut dengan perihal
keislaman. Semacam kisah-kisah yang, saya rasa, belum lama ini nge-pop—selain
kisah inspiratif—dan getol diceritakan novelis kita, sebut saja Habiburrahman El
Shirazy atau Andrea Hirata dengan novel-novel inspiratifnya. Dan, sudah barang
tentu, genre novel semacam itu banyak diikuti oleh para novelis muda Indonesia,
juga oleh teman-teman KPI 2012 dalam cerpennya.
Di
dalam buku ini, saya mendapati judul-judul cerpen semisal “Kecupan Hidayah
Khumairoh” karya Indri Yunita, atau cerita penantiannya Lilis Sarifatul A. yang
bertajuk “Purnama Dini Hari”. Namun setelah saya buka halaman-halaman
berikutnya, saya mendapati cerpen yang boleh jadi membuat kita teringat kembali
pada Sitti Nurbaya-nya Marah Rusli, atau kisah Tenggelamnya Kapal van
Der Wijk milik Hamka, atau cerita tentang Romeo and Juliet karya William
Shakespeare. Saya mendapati cerpen yang bertajuk “Surat untuk Calon Ibu Mertua”
yang ditulis oleh Qurrotul Aini. Aini menceritakan tentang kisah cinta sepasang
manusia yang tak mendapat restu keluarga. Lihat saja, Aini menuliskan kalimat:
.....Sebelum Mas Ugi berangkat ke luar negeri, ia memang
sudah memperkenalkan Najaah pada orang tuanya. Namun pertemuan itu menyisihkan
kepedihan yang amat sulit untuk dilupakan. Ibu Ugi tidak setuju dengan hubungan
mereka. Dengan alasan, Najaah bukanlah anak yang berpendidikan
Sepertinya, apa yang telah diceritakan oleh
Marah Rusli, Hamka, Shakespeare, ataupun Aini, memang masih terjadi di abad 21
ini. Kita tahu, kisah cinta dua orang manusia terkadang dipertemukan dengan
problem perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras, status sosial, latar
belakang pendidikan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Saya kira, apa yang telah
diceritakan oleh Aini dalam buku ini, juga merupakan suatu bentuk kritik
sosial. Dan, rupanya tidak hanya Aini yang menyampaikan kritiknya lewat cerpen,
Laela Nur Istiqomah
pun menyampaikan hal yang demikian. Coba kita lihat paragraf terkahir cerpen
milik Laela yang bertajuk “Prahara”:
.....Bu Nani duduk di depan teras belakang, sambil
menatap ranting yang menguning, dan memikirkan nasib rumah tangganya yang
awalnya terasa manis, seakan menemukan sosok seorang suami yang sempurna bagai
Malaikat. Tapi waktu telah mengubahnya jadi preman kasar yang setiap hari
membuat Bu Nani ‘makan hati’. Sambil nenarik nafas panjang ia mulai memasrahkan
kepada Sang Pencipta untuk menjalani semua takdir yang terjadi, sekali pun
suaminya takkan pernah berubah.
Dengan
terang Laela menceritakan persoalan rumah tangga sebuah keluarga yang tidak harmonis.
Kita tahu, dalam setiap kehidupan rumah tangga memang selalu muncul
permasalahan. Maka, menciptakan dan menjaga sebuah keharmonisan merupakan langkah
yang tepat. Dan, mungkin Laela pun bermaksud demikian: mengingatkan akan
pentingnya keharmonisan dalam keluarga, dalam kehidupan.
Selain
itu, ada pula cerita “Cinta Suci Rositi” milik Juli Ibnu Alkamzy yang berisikan
pesan-pesan kebajikan. Hampir dalam setiap dialog dalam cerpennya, Juli menganjurkan
pada kita untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan apa yang telah diajarkan
oleh agama Islam. Saya kira, mungkin Juli hendak berdakwah lewat cerpennya.
Sungguh baik. Namun, bukankah suatu karya yang baik dapat menyembunyikan
maksudnya. Jadi, makin banyak maksud-maksud yang dapat disembunyikan, maka
karya tersebut dianggap makin berkualitas (Nyoman Kutha Ratna, 2009: 246).
Saya
pun pernah mendengar bahwa, cerita yang baik ialah cerita yang menyajikan
imajinasi yang baik pula bagi pembacanya. Kemudian, setelah saya perhatikan,
cerpen-cerpen yang terhimpun dalam bunga rampai ini sepertinya menyajikan imaji
yang membumi: imaji yang realistis. Cerita-cerita yang mereka sampaikan, saya
rasa, baik dan sederhana. Dengan sederhana, mereka menyampaikan realita
kehidupan. Realita kehidupan yang kadang tidak adil, menyusahkan, dan membuat
mereka muak. Dan, rasa muak itu mereka ceritakan dalam buku ini. Seperti yang
diceritakan oleh Laela dalam “Prahara”. Di mana seorang istri yang mesti tabah
menghadapi polah suaminya yang selalu saja mabuk-mabukan, tak juga sadar, tak
kunjung menemu hidayah-Nya. Ya, semacam cerita-cerita yang sering kita jumpai dalam
sinetron. Saya pikir, mereka telah berkata jujur sesuai dengan pengindraannya. Mereka
tidak ingin muluk-muluk dalam bercerita.
Berbicara mengenai tayangan sinetron, dalam buku ini, Juni Riri Evriana menyampaikan pendapatnya dengan serius soal tayangan sinetron. Mari kita simak ketika Juni Riri menyerukan kegeramannya lewat satu alinea dalam esainya yang bertajuk “Siaran Televisi: Ancaman Generasi Muda Indonesia”:
Saya katakan, tidak sedikit tayangan televisi di Indonesia bermutu rendah. Banyak tayangan-tayangan yang tidak layak ditonton, misalnya program acara yang menayangkan acara gaib, acara-acara musik, tayangan sinetron, dan program acara lainnya. Tayangan semacam itu saya kira, tidak memberikan pengetahuan dan manfaat yang lebih. Sangat sedikit bahkan hampir tidak ada tayangan televisi di Indonesia yang memberikan ruang untuk pendidikan anak-anak. Ini memprihatinkan menurut saya, karena seharusnya televisi menjadi media pendidikan untuk generasi penerus bangsa kita.
Tentu, kita pun sepakat dengan apa yang telah diserukan oleh Juni Riri dalam esainya itu. Kita tahu, pasca ditetapkannya kebebasan pers tahun ‘98, media massa—baik cetak maupun elektronik—bertingkah sebebas-bebasnya, sewenang-wenangnya, lepas dari kontrol. Akhirnya, fungsi utama dari media massa yang memberikan penjelasan tentang berbagai peristiwa kepada masyarakat, telah terdistorsi sedemikian rupa. Media massa telah mendistorsi kebenaran menjadi suatu realitas yang fiktif. Karena, menurut Nyoman (2009: 327), bagi media massa seolah-olah tidak ada perbedaan antara yang fakta dan yang fiksi. Oleh karena itu, banyak kita jumpai pelarangan terhadap media massa karena dianggap telah melanggar norma-norma tertentu. Misal, peristiwa yang sempat terjadi pada TV One, yang kemudian diserbu warga lantaran menayangkan hasil Quick Count yang nyleneh pada Pilpres 2014. Imbasnya, muncul keragu-raguan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap validitas berita-berita yang disajikan.
Berbicara mengenai tayangan sinetron, dalam buku ini, Juni Riri Evriana menyampaikan pendapatnya dengan serius soal tayangan sinetron. Mari kita simak ketika Juni Riri menyerukan kegeramannya lewat satu alinea dalam esainya yang bertajuk “Siaran Televisi: Ancaman Generasi Muda Indonesia”:
Saya katakan, tidak sedikit tayangan televisi di Indonesia bermutu rendah. Banyak tayangan-tayangan yang tidak layak ditonton, misalnya program acara yang menayangkan acara gaib, acara-acara musik, tayangan sinetron, dan program acara lainnya. Tayangan semacam itu saya kira, tidak memberikan pengetahuan dan manfaat yang lebih. Sangat sedikit bahkan hampir tidak ada tayangan televisi di Indonesia yang memberikan ruang untuk pendidikan anak-anak. Ini memprihatinkan menurut saya, karena seharusnya televisi menjadi media pendidikan untuk generasi penerus bangsa kita.
Tentu, kita pun sepakat dengan apa yang telah diserukan oleh Juni Riri dalam esainya itu. Kita tahu, pasca ditetapkannya kebebasan pers tahun ‘98, media massa—baik cetak maupun elektronik—bertingkah sebebas-bebasnya, sewenang-wenangnya, lepas dari kontrol. Akhirnya, fungsi utama dari media massa yang memberikan penjelasan tentang berbagai peristiwa kepada masyarakat, telah terdistorsi sedemikian rupa. Media massa telah mendistorsi kebenaran menjadi suatu realitas yang fiktif. Karena, menurut Nyoman (2009: 327), bagi media massa seolah-olah tidak ada perbedaan antara yang fakta dan yang fiksi. Oleh karena itu, banyak kita jumpai pelarangan terhadap media massa karena dianggap telah melanggar norma-norma tertentu. Misal, peristiwa yang sempat terjadi pada TV One, yang kemudian diserbu warga lantaran menayangkan hasil Quick Count yang nyleneh pada Pilpres 2014. Imbasnya, muncul keragu-raguan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap validitas berita-berita yang disajikan.
Saya
pikir, fenomena tersebut merupakan dampak dari hegemoni media massa. Media
massa, kini telah menjadi alat kekuasaan baik bagi seseorang maupun kelompok
tertentu. Dan, tentu kita gusar melihat fenomena semacam itu. Lantas, kegusaran
kita pada akhirnya terwakili oleh Juni Riri dalam esainya.
Kegusaran pada realitas disampaikan pula oleh Lailatul Khoiroh dalam esainya yang bertajuk “Film Kartun Vs Perkembangan Anak”. Ya, mereka berdua berbicara soal media massa. Juni Riri menilai siaran televisi, sedangkan Lailatul Khoiroh mengangkat film sebagai pokok permasalahan dalam esainya. Selain itu, mereka pun berbarengan menyindir soal pendidikan terhadap anak: bagaimana atau seperti apa pendidikan yang baik, yang mesti diberikan pada anak-anak di tengah era informasi ini. Kemudian, pembahasan mereka dilanjutkan secara terperinci oleh Indri Yunita dalam esainya yang bertajuk “Orangtua: Penguji Teori Tabula rasa”. Di dalam esainya, Indri menguraikan perihal mendidik anak. Hal itu terlihat pada sub-sub judul esainya. Indri menyampaikan bagaimana memahami jiwa anak dan seperti apa peran orang tua dalam perkembangan anak. Tak hanya itu, Indri pun sedikit memberikan penjelasan tentang teori tabula rasa, teori yang digagas oleh John Locke.
Dalam kumpulan esai teman-teman KPI 2012 ini, saya pun menemukan perbincangan yang menarik soal emansipasi wanita: gagasan yang dicetuskan oleh si gadis Jepara, yang kemudian dipraktikkan dengan sempurna oleh Siti Soendari dalam Rumah Kaca-nya Pramoedya Ananta Toer. Perbincangan itu digarap oleh dua mahasiswi yang bernama Lilis Sarifatul A. dengan esainya yang bertajuk “Persaingan Melawan Kaum Superior”, dan Iim Rohimah dengan esainya yang ia beri judul “Pilihan Wanita Modern: Ibu Rumah Tangga atau Karir?”.
Lilis menyampaikan kritik pedasnya tentang emansipasi wanita. Lilis merasa prihatin melihat ambisi menggebu dalam diri wanita masa kini yang memperjuangkan persamaan bahkan menaikkan hak-haknya di atas kaum adam—yang disebut oleh Lilis sebagai kaum superior. Keprihatinan Lilis muncul ketika ia memperhatikan realitas di hadapannya; ketika wanita akhirnya mampu menggeluti profesi para pria, semisal menjadi pegulat, pesepak bola, dan lainnya. Saya kira, Lilis ingin mengatakan bahwa emansipasi wanita tidak perlu dicapai dengan perjuangan mati-matian semacam itu.
Di dalam esainya, Lilis sedikit menyinggung perihal kekerasan simbolik yang dialami oleh wanita. Pendapat Lilis itu bisa kita jumpai dalam sub-judul esainya, yaitu iklan sebagai bentuk kekerasan terselubung. Wanita yang menjadi model iklan, kata Lilis, mengalami suatu bentuk kekerasan simbolik. Kekerasan yang menurut Lilis lebih berakibat fatal ketimbang kekerasan fisik. Namun perlu kita ketahui pula bahwa, ketika menggunakan istilah ‘simbolik’ dalam suatu pengertian yang paling umum, orang menganggap bahwa memberi tekanan kepada kekerasan simbolik sama saja dengan meminimalkan peran kekerasan fisik, dan sama saja dengan (membuat orang) melupakan fakta bahwa memang ada perempuan-perempuan yang dipukuli, diperkosa, dieksploitasi, atau sama dengan membebaskan laki-laki dari dosa telah melakukan bentuk-bentuk kekerasan semacam itu (Pierre Bourdieu, 2010: 49). Kata Bourdieu, jelas bukan itu persoalannya.
Pembahasan soal emansipasi wanita disampaikan pula secara singkat oleh Iim Rohimah. Iim, dalam esainya, mempertanyakan atau lebih tepatnya memberikan dua buah pilihan untuk para wanita di zaman modern ini. Pilihan antara ibu rumah tangga atau karir. Sepertinya, apa yang disampaikan oleh Iim selaras dengan pendapat Ahmad Zayadi dalam Jurnal Yin Yang (2012: 198) yang menyatakan bahwa, pembakuan peran perempuan sebagai the second sex dan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga mulai mengalami pergeseran. Saat ini, kita tahu, perempuan sudah mulai banyak mengaktualisasikan dirinya melalui banyak bidang, seperti yang telah disebutkan di atas.
Apa yang telah disampaikan oleh teman-teman KPI 2012 dalam esainya, saya rasa, amatlah baik. Mereka menyampaikan kritik atau tanggapannya terhadap realitas dengan baik dan lugas. Lagi, wacana tentang emansipasi wanita kembali disampaikan oleh Nurida Ismawati lewat karya tulis ilmiahnya yang bertajuk “Pandangan KH. Husain Muhammad: Membela Perempuan dalam Pesantren”. Menurut Nurida, gagasan yang diusung oleh KH. Husain Muhammad agak berbeda dari feminis Islam lainnya. Gagasan yang diusung oleh beliau, KH. Husain Muhammad, disesuaikan dan/atau berdasar pada kearifan lokal, semisal pesantren. Kita pun tahu, tidak sedikit literatur-literatur di pesantren yang membahas kedudukan seorang perempuan dalam Islam, sebut saja salah satu kitab klasik (kitab kuning) ‘Uqud al-Lujjayn karangan Mbah Nawawi Banten. Kitab fiqh itu, singkatnya lebih banyak membahas perihal kewajiban seorang perempuan (istri) dalam melayani suaminya. Saya kira, apa yang disampaikan oleh Nurida lewat pandangan KH. Husain Muhammad merupakan kritik terhadap literatur-literatur di dunia pesantren. Kritik pula bagi masyarakat pesantren dalam memposisikan perempuan. Dan, kita tahu, kritik terhadap teks-teks agama terkadang dianggap sebagai tindakan yang kurang santun. Namun, itu dilakukan oleh KH. Husain Muhammad. Mungkin, itu pula yang menyebabkan Nurida tertarik mencermati serta menyampaikan pandangan KH. Husain Muhammad soal pembelaan terhadap perempuan.
Ya, apa yang disampaikan oleh Lilis dan Iim dalam karya esai, kembali disampaikan lebih mendalam—juga dari sudut pandang yang berbeda—oleh Nurida lewat karya tulis ilmiah. Namun, ketiganya menyampaikan wacana yang serupa: emansipasi wanita. Tidak hanya mereka bertiga, semuanya—hampir semua penulis dalam buku ini—memberi tanggapan (kritik) terhadap keadaan di sekitarnya. Jadi, seperti yang telah disinggung di depan bahwa, antara satu bentuk karya dengan bentuk karya yang lain; dari karya puisi hingga ke karya tulis ilmiah, semuanya saling berkaitan dan memiliki keseragaman dalam memprotes keadaan. Saya kira, saya telah menemukan keunikan di dalam bunga rampai ini.
Saya sampaikan selamat untuk teman-teman KPI 2012 karena telah menghadirkan keunikan pada buku ini. Saya berharap, semoga teman-teman KPI 2012 dapat terus meningkatkan budaya literasi di kampus STAIN Purwokerto, di tengah vitalitas zaman yang edan. Semoga teman-teman tidak terlena oleh suguhan gadget dan pengaruh buruk modernitas lainnya. Sehingga, teman-teman tidak kecolongan waktu untuk terus berkarya; merekam dan mengukir sejarah lewat tulisan.
Kegusaran pada realitas disampaikan pula oleh Lailatul Khoiroh dalam esainya yang bertajuk “Film Kartun Vs Perkembangan Anak”. Ya, mereka berdua berbicara soal media massa. Juni Riri menilai siaran televisi, sedangkan Lailatul Khoiroh mengangkat film sebagai pokok permasalahan dalam esainya. Selain itu, mereka pun berbarengan menyindir soal pendidikan terhadap anak: bagaimana atau seperti apa pendidikan yang baik, yang mesti diberikan pada anak-anak di tengah era informasi ini. Kemudian, pembahasan mereka dilanjutkan secara terperinci oleh Indri Yunita dalam esainya yang bertajuk “Orangtua: Penguji Teori Tabula rasa”. Di dalam esainya, Indri menguraikan perihal mendidik anak. Hal itu terlihat pada sub-sub judul esainya. Indri menyampaikan bagaimana memahami jiwa anak dan seperti apa peran orang tua dalam perkembangan anak. Tak hanya itu, Indri pun sedikit memberikan penjelasan tentang teori tabula rasa, teori yang digagas oleh John Locke.
Dalam kumpulan esai teman-teman KPI 2012 ini, saya pun menemukan perbincangan yang menarik soal emansipasi wanita: gagasan yang dicetuskan oleh si gadis Jepara, yang kemudian dipraktikkan dengan sempurna oleh Siti Soendari dalam Rumah Kaca-nya Pramoedya Ananta Toer. Perbincangan itu digarap oleh dua mahasiswi yang bernama Lilis Sarifatul A. dengan esainya yang bertajuk “Persaingan Melawan Kaum Superior”, dan Iim Rohimah dengan esainya yang ia beri judul “Pilihan Wanita Modern: Ibu Rumah Tangga atau Karir?”.
Lilis menyampaikan kritik pedasnya tentang emansipasi wanita. Lilis merasa prihatin melihat ambisi menggebu dalam diri wanita masa kini yang memperjuangkan persamaan bahkan menaikkan hak-haknya di atas kaum adam—yang disebut oleh Lilis sebagai kaum superior. Keprihatinan Lilis muncul ketika ia memperhatikan realitas di hadapannya; ketika wanita akhirnya mampu menggeluti profesi para pria, semisal menjadi pegulat, pesepak bola, dan lainnya. Saya kira, Lilis ingin mengatakan bahwa emansipasi wanita tidak perlu dicapai dengan perjuangan mati-matian semacam itu.
Di dalam esainya, Lilis sedikit menyinggung perihal kekerasan simbolik yang dialami oleh wanita. Pendapat Lilis itu bisa kita jumpai dalam sub-judul esainya, yaitu iklan sebagai bentuk kekerasan terselubung. Wanita yang menjadi model iklan, kata Lilis, mengalami suatu bentuk kekerasan simbolik. Kekerasan yang menurut Lilis lebih berakibat fatal ketimbang kekerasan fisik. Namun perlu kita ketahui pula bahwa, ketika menggunakan istilah ‘simbolik’ dalam suatu pengertian yang paling umum, orang menganggap bahwa memberi tekanan kepada kekerasan simbolik sama saja dengan meminimalkan peran kekerasan fisik, dan sama saja dengan (membuat orang) melupakan fakta bahwa memang ada perempuan-perempuan yang dipukuli, diperkosa, dieksploitasi, atau sama dengan membebaskan laki-laki dari dosa telah melakukan bentuk-bentuk kekerasan semacam itu (Pierre Bourdieu, 2010: 49). Kata Bourdieu, jelas bukan itu persoalannya.
Pembahasan soal emansipasi wanita disampaikan pula secara singkat oleh Iim Rohimah. Iim, dalam esainya, mempertanyakan atau lebih tepatnya memberikan dua buah pilihan untuk para wanita di zaman modern ini. Pilihan antara ibu rumah tangga atau karir. Sepertinya, apa yang disampaikan oleh Iim selaras dengan pendapat Ahmad Zayadi dalam Jurnal Yin Yang (2012: 198) yang menyatakan bahwa, pembakuan peran perempuan sebagai the second sex dan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga mulai mengalami pergeseran. Saat ini, kita tahu, perempuan sudah mulai banyak mengaktualisasikan dirinya melalui banyak bidang, seperti yang telah disebutkan di atas.
Apa yang telah disampaikan oleh teman-teman KPI 2012 dalam esainya, saya rasa, amatlah baik. Mereka menyampaikan kritik atau tanggapannya terhadap realitas dengan baik dan lugas. Lagi, wacana tentang emansipasi wanita kembali disampaikan oleh Nurida Ismawati lewat karya tulis ilmiahnya yang bertajuk “Pandangan KH. Husain Muhammad: Membela Perempuan dalam Pesantren”. Menurut Nurida, gagasan yang diusung oleh KH. Husain Muhammad agak berbeda dari feminis Islam lainnya. Gagasan yang diusung oleh beliau, KH. Husain Muhammad, disesuaikan dan/atau berdasar pada kearifan lokal, semisal pesantren. Kita pun tahu, tidak sedikit literatur-literatur di pesantren yang membahas kedudukan seorang perempuan dalam Islam, sebut saja salah satu kitab klasik (kitab kuning) ‘Uqud al-Lujjayn karangan Mbah Nawawi Banten. Kitab fiqh itu, singkatnya lebih banyak membahas perihal kewajiban seorang perempuan (istri) dalam melayani suaminya. Saya kira, apa yang disampaikan oleh Nurida lewat pandangan KH. Husain Muhammad merupakan kritik terhadap literatur-literatur di dunia pesantren. Kritik pula bagi masyarakat pesantren dalam memposisikan perempuan. Dan, kita tahu, kritik terhadap teks-teks agama terkadang dianggap sebagai tindakan yang kurang santun. Namun, itu dilakukan oleh KH. Husain Muhammad. Mungkin, itu pula yang menyebabkan Nurida tertarik mencermati serta menyampaikan pandangan KH. Husain Muhammad soal pembelaan terhadap perempuan.
Ya, apa yang disampaikan oleh Lilis dan Iim dalam karya esai, kembali disampaikan lebih mendalam—juga dari sudut pandang yang berbeda—oleh Nurida lewat karya tulis ilmiah. Namun, ketiganya menyampaikan wacana yang serupa: emansipasi wanita. Tidak hanya mereka bertiga, semuanya—hampir semua penulis dalam buku ini—memberi tanggapan (kritik) terhadap keadaan di sekitarnya. Jadi, seperti yang telah disinggung di depan bahwa, antara satu bentuk karya dengan bentuk karya yang lain; dari karya puisi hingga ke karya tulis ilmiah, semuanya saling berkaitan dan memiliki keseragaman dalam memprotes keadaan. Saya kira, saya telah menemukan keunikan di dalam bunga rampai ini.
Saya sampaikan selamat untuk teman-teman KPI 2012 karena telah menghadirkan keunikan pada buku ini. Saya berharap, semoga teman-teman KPI 2012 dapat terus meningkatkan budaya literasi di kampus STAIN Purwokerto, di tengah vitalitas zaman yang edan. Semoga teman-teman tidak terlena oleh suguhan gadget dan pengaruh buruk modernitas lainnya. Sehingga, teman-teman tidak kecolongan waktu untuk terus berkarya; merekam dan mengukir sejarah lewat tulisan.
Tanjungpinang,
Agustus 2014
*Tulisan ini merupakan epilog (bagian penutup)
buku Pohon Dakwah 2: Bunga Rampai Karya Tulis Ilmiah, Esai, Cerpen, dan
Puisi, karya mahasiswa KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam) angkatan tahun
2012, kampus IAIN Purwokerto.




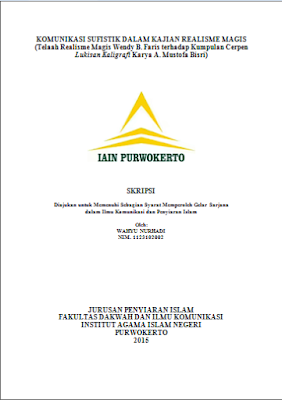
Comments