Meditasi*
oleh Wahyu Noerhadi
“Ini
acara selesai jam berapa, Mas?” sapa pemuda di depanku sembari menengok ke arlojinya.
“Di
manual acaranya sih sampai jam
dua belas, tapi kebiasaan kita ‘kan mulur. Jadi, ya, paling banter kita selesai
jam tiga pagi kayaknya Mas. Ho-ho-ho,” jawabku kepada pemuda yang belum
kuketahui namanya itu.
Percakapan
itu terjadi sesaat sebelum aku mencolek pipi kiri Ayu, teman sekelasku yang juga
kekasih dari pemuda yang belum kuketahui namanya itu. Kemudian, dengan air muka
yang tak bisa kujelaskan, pemuda itu bangkit dari kursi dan tiba-tiba menepuk
pundakku, lalu mengajakku ke luar ruangan.
“Kalau
memang lelaki, ayo kita selesaikan di sini!” geretak pemuda itu dengan
tangannya mencengkeram kerah bajuku.
“Lho, lho, lho, Mas...”
Belum
selesai aku bicara. Buuuggg. Satu
tinju mendarat di pipi kiriku. Aku kebingungan dan pemuda itu terus saja meracau
sambil mengendurkan kerah bajuku, dan berlalu. Ayu, yang berdiri tegap di
belakangku ikut berlalu bersama kekasihnya itu.
Dari
kejauhan racauannya masih saja dapat terdengar, “silakan lapor polisi. Anak
buahku pasti akan mencarimu!” Ancam pemuda itu sembari mengacung-ngacungkan
telunjuknya.
Dia
pergi menggandeng Ayu. Aku kembali masuk ruangan dengan membawa perasaan yang aneh.
Ditambah, adanya kesaksian dari Rizki dan Ivan, sahabatku yang melihat kejadian
itu. Geram, malu, dan lucu, semuanya campur aduk jadi satu.
“Ada
apa tadi di luar?” tanya Janu, penasaran.
“Ada
orang marah-marah.”
“Gara-gara
apa?”
“Mungkin
karena aku bercanda dengan perempuannya.”
“Bicara
apa saja dia?”
“Entahlah.”
“Pipi
kirinya jadi sasaran Jan,” potong Rizki, dengan mengarahkan dagunya ke wajahku.
Janu
terhenyak dan Ardi naik darah.
“Kita
cari anaknya sekarang!” Hemat Ardi yang seketika itu wajahnya menjadi merah.
“Nanti
saja, jangan sekarang,” cegahku dengan detak jantung yang sedari tadi masih
saja belum teratur.
Di
depan, acara sarasehan sastra terus berlanjut. Sedangkan di belakang, keadaan
menjadi sedikit riuh.
Setelah
kondisi di belakang agak tenang, tibalah Ivan dan Tio dari kursi seberang.
“Oi,
katanya kau kena pukul? Pacarnya Ayu? Namanya siapa? Anak mana?”
Tio
memberondongku dengan pertanyaannya. Aku hanya menganggukkan kepala lantas mengangkat
bahu.
Tio,
temanku yang satu ini sangat dekat sekali dengan hal-hal yang berbau mistik. Dan
Ardi memulai lagi,
“Sepertinya
dia memang berisi.”
Tentu
saja Tio meng-iya-kan.
Kursi
belakang kembali riuh dan aku masih diinterogasi. Aku menjawab sekenanya, dan
sesingkat-singkatnya, karena aku memang masih tidak mengerti dengan apa yang
terjadi di luar ruangan tadi. Wajahku kena tinju, pikirku. Dan, aku masih ingat
kapan terakhir kali aku berkelahi. Ya, ketika aku masih duduk di kelas 3 SMP,
itu terakhir kalinya.
Aku
memang tidak gemar berkelahi, namun bagaimana bisa, aku yang sudah sebesar ini
masih bisa kena pukul orang. Apalagi gara-gara soal sepele semacam itu. Rizki,
Janu, Ardi, dan Tio pun tak henti-hentinya memojokanku, agar aku membalas
perlakuan pemuda itu. Tanpa harus memandang dia kekasih temanku.
Pikiranku
benar-benar tidak karuan saat itu. Dan, entah sejak kapan telepon genggamku
bergetar. Setelah aku menyadarinya, ada dua pesan masuk tanpa nama. Dua pesan itu
mengatas-namakan Ayu dan terus menyebut-nyebutkan nama: ayah, yang ternyata
nama panggilan yang dipakai oleh Ayu kepada kekasihnya itu, pemuda yang belum
lama menghantam pipi kiriku. Ayah, nama panggilannya. Aku sedikit terkekeh karena
nama panggilan itu, sekaligus terheran ketika selesai membaca kedua pesannya.
***
Pesan
1: Yu, aku minta maaf atas kejadian tadi.
Semua itu gara-gara kamu, karena mencolek pipiku dan Ayah tahu. Ayah itu nggak
suka kalau aku sampai disentuh, disenggol, dicolek, ditabrak sama cowok,
siapapun itu. Ayah itu bermaksud menjaga aku, biar nggak gampang bersentuhan
sama cowok, walaupun itu nggak sengaja. Ketika Ayah sedang nggak sama aku pun,
dia tahu apa yang terjadi sama aku. Ayah itu punya kebatinan yang tajam. Tolong,
kejadian ini nggak usah dibesar-besarkan. Nggak usah diceritakan ke
siapa-siapa. Takutnya kalau masalah ini dibesar-besarkan, ada apa-apanya, kamu
yang bahaya Yu. Ayah orangnya nekat banget. Riwayatnya juga mantan preman,
sampai pernah nusuk 3 orang di Cilacap. Sekali lagi aku minta maaf ya!
“Kau
kenapa, tersenyum-senyum seperti itu?” Rizki mengagetkanku.
“Ini,
si Ayu SMS,” sembari kusodorkan telepon genggamku padanya.
Tio,
Ardi, dan Janu turut serta menyodorkan kepalanya ke layar telepon genggamku.
“Wah,
sepertinya ilmumu belum seberapa jika dibandingkan dengannya,” ledek Janu pada Tio.
“Baik.
Aku harus cari tahu siapa gurunya. Bha-ha-ha,” balas Tio.
“Aduh,”
Rizki menggeleng-gelengkan kepalanya, “baru juga pacaran, bagaimana kalau nanti
sudah berkeluarga? Repot, repot. Pasti setiap cowok yang bersentuhan dengan Ayu
kena tinju. Orang yang hanya bersalaman dengan Ayu, pasti juga kena tinju.
Bisa-bisa Bapaknya Ayu pun kena tinju.”
Pesan
2: Tolong ya Yu, masalah ini jangan
sampai dibesar-besarkan. Takutnya kamu juga diapa-apain Ayah dari jauh. Ayah
sih orangnya kalau ditantang nggak takut sama sekali, malah tambah nekat. Aku
bukan sedang pamer, tapi Ayah orangnya memang keras. Dari kecil dia sudah biasa
bertapa. Dia turunan Jawa asli, masih berdarah Majapahit.
“Ha-ha-ha.
Ini curiculum vitae pacaranya si Ayu?
Dikira kita ngeper. Hah?” Janu memulai
lagi.
“Tenang,
tenang. Kita akan kirim sesuatu ke dia. Pesan itu jangan dulu dihapus!” Tegas Tio
dengan wajah yang sedikit serius.
“Belum
tahu dia, Prabu Siliwangi siapanya Ayahku,” lanjut Janu.
“Ah.
Aku tidak ingin main-main. Kalau memang kalian berani, sekarang lebih baik kita
cari dia!” Ardi bangkit dengan wajah yang kembali merah.
“Ar,
Ar, Ar. Tahan dulu,” Ivan yang sedari tadi diam tiba-tiba mengeluarkan suaranya,
“jika dia dan anak buahnya memulai, baru kita bertindak. Untuk sekarang, kita
diam dan tunggu saja apa yang akan dia lakukan.”
Ardi
kembali duduk dan omongan Ivan ternyata membuat kami semua diam, tidak lagi
membicarakan kejadian di luar ruangan itu sampai acara selesai, pukul 03.00
pagi.
***
Setibanya
di kos, aku tidak bisa langsung memejamkan mata. Kepalaku rasanya masih belum
bisa tenang. Kepalaku terus-menerus menggambarkan bagaimana pemuda itu
menggeretakku dan seketika itu aku seperti tersihir, sehingga membuat wajahku
menjadi sasaran tinjunya tanpa sempat membalasnya. Sebenarnya, akibat dari
tinju itu tidak seberapa dan sama sekali tidak mengubah bentuk wajahku. Tapi,
peristiwa itu disaksikan oleh teman-temanku, juga Ayu. Harga diri seorang
lelaki kiranya patut dijadikan pertimbangan untuk melanjutkan persoalan ini. Tapi,
masih pantaskah gara-gara hal sepele semacam itu, kemudian harga diri dijadikan
alasan? Dan, aku pun tak tahu akibatnya nanti, jika aku bersikeras
mengedepankan harga diriku. Ah, apa yang mesti kulakukan?
Entah
mengapa, sesaat sebelum mataku terpejam, rasa-rasanya aku ingin kembali membaca
kedua pesan itu. Dan, seperti dengan sendirinya tanganku menekan-nekan keypad telepon genggamku. Setelah
selesai membacanya aku kembali terkekeh-kekeh dan merasa aneh. Aku memang masih
heran sekaligus meragukan hal-hal mistik yang dimiliki pemuda itu. Ah, kepalaku
kembali terusik.
Aku
berpikir, mungkin Ayu hanya mengada-ngada saja, supaya masalah ini selesai
sampai di sini. Agar aku diam dan rela menerima perlakuan kekasihnya. Bah, tidak
akan. Peringatan Ayu sepertinya malah menguatkan tekadku untuk membalas
perlakuan kekasihnya itu. Lihat saja besok di kelas. Bagaimana jika pipi
kirinya Ayu itu, aku cium. Apa yang akan diperbuat oleh kekasihnya itu.
Ha-ha-ha-ha.
Aku
belum sampai lelap, kemudian dibangunkan oleh getaran telepon genggamku. Tanda pesan
masuk. Aku buka pesannya, dan berbunyi seperti ini: Yu, kata Ayah, Ayah baru saja selesai meditasi. Ayah dapat petunjuk,
siapa-siapa aja yang menyaksikan kejadian itu, seperti Rizki dan Ivan. Hasil
meditasinya, kata Ayah, si Rizki lahir hari Senin Pon, dan si Ivan Sabtu Pahing.
Kamu sendiri lahirnya hari Jum’at Kliwon.
Aku
mengingat-ngingat hari lahirku. Dan benar, Jum’at Kliwon adalah hari lahirku.
*Cerpen ini dimuat di harian Satelit Post



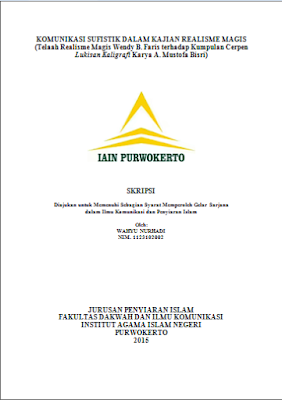
Comments