Tara Basro dan Dampak Komodifikasi Media
 |
| Sumber gambar: instagram.com/tarabasro |
Standar kecantikan ideal yang dikonstruksi—sekaligus dieksploitasi—oleh
media itu tidak lain adalah bentuk komodifikasi. Prinsip komodifikasi diartikan
sebagai proses transformasi nilai guna jadi nilai tukar. Vincent Mosco (1996)
menyebut, komodifikasi ini sebagai kegiatan produksi dan distribusi komoditas
yang lebih mempertimbangkan daya tarik, agar banyak dipuja oleh orang dibandingkan
dengan fungsinya sendiri sebagai barang dagangan.
Satu contoh yang jamak dimafhumi, wanita ideal selalu
dicitrakan berkulit putih atau kuning langsat, tinggi dan berbodi bak top model
yang berlenggang di arena catwalk. Orang kita biasanya menyebut wanita
dengan ciri-ciri di atas dengan akronim yang mengarah kepada nama burung kecil
berbunyi nyaring: Kutilang (kuning, tinggi, langsing).
Tentu sudah sejak lama konstruksi itu berjalan.
Ya, kita tahu, pada akhirnya konstruksi dan komodifikasi media adalah strategi
dalam bisnis-industri semata.
Dalam perjalanannya, industri media sendiri
yang menciptakan standar wanita ideal, yang kemudian standar itu
didistribusikan kepada khalayak, lewat tayangan televisi, foto model di
majalah, obrolan penyiar di radio, dan seterusnya.
Dampaknya, kita tahu sendiri, tidak sedikit wanita
yang mati-matian atau setengah mati ingin mengikuti standar yang disuguhkan
media itu. Tentu, tiap manusia punya isi kepala dan kehendak masing-masing. Maka itu, di sini saya bukan hendak mengatakan, berceramah, bahkan melarang
siapa pun untuk tidak mengikuti standar yang ditetapkan media soal idealnya wanita.
Siapa saya? Dan, seperti saya katakan di atas, tiap pribadi punya batok kepala
sendiri-sendiri. Saya hanya dongkol saja dengan tingkah-polah media yang
membikin kita jadi masyarakat konsumtif; yang nrimo saja apa yang disuguhkan media.
Berbarengan dengan itu, muncul pula fenomena beauty
privilege di tengah masyarakat kita terhadap wanita yang dianggap ideal
oleh media. Ditambah dengan adanya media sosial yang tak henti-henti
membombardir kita dengan jutaan konten. Di antaranya konten soal kecantikan dan
keglamoran, yang kemudian memunculkan kelompok wanita high class dalam ruang
media sosial. Fenomena ini jika dilanjutkan terus-menerus akan menjadikan
kelompok wanita ini merasa high demand.
Beauty privilege ini seperti
pisau bermata dua; di satu sisi kadang menjadi baik dan memudahkan wanita dalam
menggapai karir atau dalam mencari pekerjaan, misalnya. Privilege itu kerap
diberikan secara cuma-cuma oleh perusahaan yang memang membutuhkan wanita
ideal. Bahkan di ruang media sosial, seorang influencer dengan segala beauty
privilege-nya serta memiliki 1 juta followers, lebih bisa dengan mudah
mendapat endorsement dari berbagai perusahaan, dibanding mereka yang
tidak mendapat predikat beauty privilege.
Sisi lain, predikat beauty privilege juga
bisa membuat kemandekan berpikir, karena saking gampangnya meraih sesuatu yang
diinginkan, sehingga kadang akan sangat sulit untuk meraih sesuatu dengan memulai
proses dari bawah. Muncul kemudian cara-cara instan dan pikiran-pikiran
instan pula; karena, yang-instan adalah koentji. Mungkin begitu.
Akibat komodifikasi media serta bombardir konten
soal beauty privilege, akhirnya muncul juga perkara body shaming
terhadap mereka yang liyan secara warna kulit, bentuk tubuh, dan hal fisik
lainnya. Perkara itu ternyata mendapat tempat, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Hal
ini menjadi dilema di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, dan
mengganggu kesadaran publik kita akhir-akhir ini, khususnya di ruang media sosial.
Akibat selanjutnya banyak dari kita akhirnya
lupa akan arti penting menjadi diri sendiri; percaya diri atas anugerah hidup
dan tubuh yang dimiliki. Tidak sedikit wanita yang mengejar standar paras ayu dan putih ideal itu dengan Oplas, berlomba-lomba mencapai
bentuk tubuh ideal dengan diet ketat—yang kadang untuk meraih semua itu, mohon
maaf, karena ada selubung insecurity di dalam diri.
Tulisan ini bermuara pada satu topik yang
kemarin (Rabu, 4 Maret 2020) sempat ramai di jagat media sosial, yaitu soal
unggahan foto di akun Twitter dan Instagram Tara Basro. Dari foto berikut caption
yang diunggah itu, saya hakul yakin, Tara Basro tengah melawan stereotip
standar kecantikan berupa beauty privilege sekaligus menghajar perkara body shaming, yang memang masih dan sering terjadi di tengah masyarakat kita hari ini. Saya tidak melihat
unggahan Tara Basro di media sosialnya seperti yang disebut Kominfo sebagai
bentuk ketelanjangan. Saya pribadi melihatnya sebagai pesan yang kuat dari dalam
diri Tara Basro dalam upaya untuk menjungkirbalikkan tatanan mapan selama ini.
Dan, dalam hal ini dia layak untuk dibela; suaru-suara itu harus tetap ada,
khususnya di media sosial yang acapkali menjadi wadah body shaming.
Penulis:
Erik Ardiyanto
Penyunting: Wahyu Noerhadi



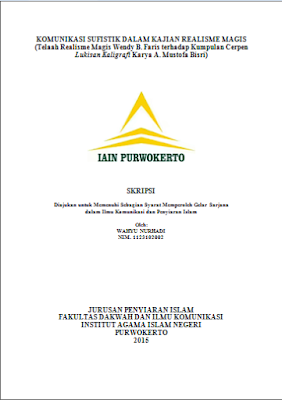
Comments