Bertamasya di Dataran Tortilla
oleh Wahyu Noerhadi
Mukadimah
Seperti di novel itu, saya pun ingin menuliskan sedikit pendahuluan atau tepatnya riwayat, perjumpaan serta kesan saya terhadap novel milik (si Sialan) John Steinbeck itu. Kelak, setelah kau membacanya, kau pun bakal menyebutnya dengan nama seperti dalam kurung itu, atau nama lain yang senada dengannya.
Begini riwayatnya: Dataran Tortilla (Tortilla Flat), saya dapatkan di Jogja. Tepatnya di toko buku JBS (Jual Buku Sastra), di jalan Wijilan, seingat saya. Teman saya memesannya saat saya sedang berada di kota istimewa itu. Nah, setelah saya selesai dengan novel dan kumpulan cerpen yang saya beli—adapun novel dan kumpulan cerpen itu ialah: Kenangan Perempuan Penghibur yang Melankolis milik Gabriel Garcia Marquez, dan kumpulan cerpen Kenangan Cinta milik Anton Chekhov—saya tentu penasaran dengan novel pesanan kawan saya itu.
Ya, saya penasaran, ingin melahap ketiga novel terjemahan itu. Jujur saja, awalnya saya memang iseng membolak-balik halaman Dataran Tortilla, untuk mendapat rangsangan membuat kalimat atau paragraf pembuka yang baik bagi proyek cerpen saya. Mengapa saya hanya iseng-iseng? Sebab, saya lumayan dibuat lelah oleh kumpulan cerpen milik Tuan Chekhov. Lelah dengan terjemahannya, juga dengan kisah-kisah yang diceritakan si pengarang asal Rusia itu, yang berkutat soal hubungan asmara manusia (pria dan wanita). Hal ini dinyatakan sendiri oleh Tuan Chekhov di dalam salah satu cerpennya, dalam buku itu. Dan, pernah saya wartakan pula bahwa, memang umumnya orang-orang Rusia gemar membicarakan hal-hal yang berat-berat dan rumit, seperti tentang kehidupan dan perempuan. Ya, itu dinyatakan sendiri olehnya, oleh Tuan Chekhov. Tapi, entahlah, saya juga belum banyak mengenal novelis-novelis Rusia.
Mungkin, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Kenangan Cinta. Akan tapi, saya telah lebih dulu dipusingkan oleh terjemahan buku itu. Saya tidak akan menyebutkan nama penerbitnya. Kurang elok rasanya jika harus diketahui oleh umum. Soal karya terjemahan, saya juga kurang terkesan dengan novel milik Gabriel Garcia Marquez, yang saya baca lebih awal dari Kenangan Cinta. Padahal, paragraf pembuka novel itu sungguhlah menarik, dan liar. Namun, di tengah cerita jadi sedikit membosankan. Sungguh berbeda nikmatnya ketika saya membaca Seratus Tahun Kesunyian, sebagai masterpiece-nya Eyang Gabo.
O ya, saya hampir lupa, di sini saya tidak hendak menceritakan soal dua novel itu atau tentang lelahnya saya membaca terjemahannya. Di sini, saya hendak bercerita mengenai Dataran Tortilla. Novel yang membuat saya takjub, terharu, dan tak jarang terpingkal-pingkal. Memang, ketika kawan saya telah lebih dulu khatam membacanya, dia juga bilang kalau novel itu keren. Ketika saya meminjamnya, dia kembali bilang keren. Dia hanya bilang “Keren!”. Ya, dengan sedikit tambahan tentunya, seperti yang jamak diucapkan orang-orang yang meminjamkan buku: “Jangan sampai rusak dan hilang!”
Namun, ketika saya akhirnya bisa merampungkan novel itu, saya tidak bisa tidak untuk memuji setinggi-tingginya si Sialan John Steinbeck atas novelnya yang satu itu. Mengapa saya selebay ini? Bukan, bukan lebay. Saya hanya ingin memujinya lantaran saya telah dibuat puas olehnya, oleh Steinbeck, oleh Dataran Tortilla. Ah, kalian mungkin akan tetap menganggap saya lebay, sebelum kalian membaca novel itu. Jadi, silakan burulah novel itu, biar saya tidak terlalu terkesan subjektif, dan kalian tidak terkesan angkuh.
Begini, bukankah kita tak asing dengan peribahasa ini: air susu dibalas dengan air tuba. Atau, pepatah yang berbunyi: jangan balas mata dengan mata. Ya, lebih-kurang seperti itu lah. Pokoknya, sudah barang tentu kita mesti senantiasa berbuat kebaikan, meski orang lain membalasnya dengan air tuba (kejahatan). Nah, apabila kejahatan pun meski kita lawan dengan kebaikan, maka kebaikan kita lawan dengan apa? Kebaikan pula tentunya.
O, maaf, saya tidak hendak berdakwah. Saya hanya bermaksud menghubungkan peribahasa dan pepatah dari Mbah Gandhi itu, dengan apa yang hendak saya lakukan saat ini. Maksudnya, saya hanya ingin membalas kebaikan Alm. John Steinbeck dengan suatu kebaikan juga. Saya ingin mengapresiasi Dataran Tortilla lewat tulisan ini. Ya, hanya tulisan semacam ini.
Tadinya, tulisan ini juga akan saya tinggal tidur, dan menyelesaikannya di lain waktu. Tapi, setelah membaringkan tubuh, ternyata kepala saya tak bisa diam. Ya, saya bisa saja melanjutkannya esok pagi, atau kapan pun. Karena, di buku catatan telah saya tulis beberapa hal yang penting dan menarik, yang ada dalam Dataran Tortilla. Jadi, saya takkan lupa. Namun, kepala saya bertanya-tanya: jika saya tinggalkan tulisan ini, apakah esok hari rasa haru terhadap novel itu masih ada?; apakah semangat di dada saya untuk mengapresiasi novel itu akan terus nyala? Saya juga memikirkan nasib tulisan ini: apakah tulisan ini akan selesai?; apakah tulisan ini bakal ada yang membacanya? Ah, saya bangkit dan mulai mengetik kembali, meski jam di laptop menunjukkan pukul 3.07 pagi. Ya, saya ingin tulisan ini selesai.
(sedikit-banyak) Tentang Dataran Tortilla
Novel itu mengambil latar di daerah ketinggian kota Monterey, sebuah kota tua di pantai California. Daerah itu bernama Dataran Tortilla. Walaupun, katanya, daerah itu sama sekali tidaklah datar. Di daerah itu tinggallah para paisano. Dalam pendahulan—yang ditulis oleh Pak Djokolelono, yang sekaligus berperan sebagai penerjemah—buku itu dijelaskan bahwa kaum paisano ialah mereka-mereka yang memiliki campuran darah Spanyol, Indian, Meksiko, dan berbagai ras kulit putih Eropa.
Kaum paisano itu di antaranya ada: Danny, Pilon, Pablo, Jesus Maria Corcoran, si Bajak Laut beserta kelima anjingnya, dan Big Joe Portugis. Mereka semua bersahabat erat, dan tinggal dalam satu rumah. Di rumah Danny. Persahabatan mereka, menurut saya, adalah persahabatan yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Di rumah itu, mereka bisa hidup rukun, dan mereka juga bisa menghajar babak belur kawannya sendiri. Lihatlah ketika mereka bersantai di rumah Danny (hlm. 197). Mereka dengan sangat khusyuk mendengarkan serta menceritakan pengalamannya masing-masing. Kalian tahu, mereka-mereka itu sangat mahir sekali bercerita. Dari cerita-cerita yang mereka sampaikan, saya sering terpingkal-pingkal dan kadang ingin meninju wajah bajingan-bajingan itu. Perlu kalian ketahui juga, kadar kelucuan cerita mereka amatlah tinggi. O ya, namun, ada juga cerita lucu yang kelucuannya tidak etis untuk ditertawai. Cerita itu disampaikan oleh Jesus Maria (hakikatnya oleh sang master, John Steinbeck) yang terdapat di halaman-halaman akhir novel.
Akan tetapi, di suatu waktu mereka juga bisa sangat beringas pada kawannya sendiri, pada si bebal Big Joe. Danny dan kawan-kawannya suatu waktu pernah menyiksa (tepatnya memberi pelajaran) Big Joe, karena telah mengambil uang empat talen milik si Bajak Laut. Danny dan kawan-kawannya memukuli Big Joe dengan kayu, hingga kayu-kayu yang mereka gunakan itu patah. Big Joe roboh, lalu pingsan. Setiap pukulan membuat kulit punggung Big Joe mengelupas. Perhatikanlah detail keberingasan Danny dan kawan-kawannya:
Danny membungkuk, mencengkeram bahunya dan menggulingkannya hingga Big Joe menelungkup. Dan kembali mereka memukulinya lagi dengan sengitnya. Jeritan Big Joe makin lama makin lemah. Tetapi mereka terus bertindak hingga Big Joe pingsan. Pilon membuka bajunya. Terlihat punggung Big Joe merah lebam. Dengan pembuka kaleng ia membuat garis-garis tipis silang menyilang, hingga pada tiap tempat yang bengkak keluar darah sedikit. Pablo mengambil garam, menggosokkannya pada punggung Big Joe. (hlm.169)
Hukuman itu tentu membuat Big Joe jera. Ya, ia tak lagi berani mencuri barang-barang para paisano di rumah Danny.
Begini, sebelum lupa melanda, izinkanlah saya untuk menuliskan beberapa hal yang tercatat dalam buku kecil saya. Dalam buku catatan itu, di bagian atas halaman, saya tulis: SERAPAN DARI STEINBECK. Di bawahnya, tentu, potongan-potongan kalimat yang saya dapatkan dari Dataran Tortilla. Sebenarnya, saya bisa saja menggaris-bawahi atau memberi stabilo tiap kalimat yang saya anggap menarik di buku itu. Tapi, apa mau dikata jika buku itu bukan milik saya? Tentu bukan sesuatu yang lucu jika kawan saya pada akhirnya memilih men-stabilo wajah saya ketimbang bukunya.
Baiklah, di bawah huruf-huruf kapital itu saya menulis hal-hal yang lucu, indah, menenteramkan, filosofis, dan sumpah serapah yang telak—yang terakhir itu jangan sampai terlewat. Ya, dalam novel terjemahan itu, Om John memperlihatkan pada saya diksi yang tepat, frasa yang akurat, lelucon-lelucon yang segar, detail yang tak membosankan, metafora-metafora yang tak klise, dan banyak lagi.
Di novel mana lagi kita bisa mendapatkan sumpah serapah seperti ini: “Sapi tua bangka!” atau “Domba tua renta!” Dan, bagaimana saya tidak tersenyum ketika mendengar pikiran Pilon tentang si Bajak Laut. Pilon berpikiran seperti ini: “Tuhan tidak menganugerahinya dengan otak yang sesuai dengan besar tubuhnya.” Dan ini: “Kasihan sekali dia. Otaknya betul-betul tak sempurna.” Tentang si Bajak Laut, Steinbeck juga menarasikannya demikian:
Tetapi seperti biasanya, bila ia mencoba memecahkan suatu persoalan otaknya terasa lumpuh, tak bisa memberinya pertolongan sedikit pun kecuali rasa putus asa. (hlm. 84)
Ya, ia memang bajingan. Steinbeck sungguh sialan. Ia juga menunjukkan frasa-frasa yang elok, misal: “relung otak” atau “dusta tulen” atau “angin mati” atau “lintang pukang” dan banyak lagi. Steinbeck juga menuliskan kalimat-kalimatnya dengan tampan, yakni sebagai berikut:
- “Otaknya simpang-siur oleh seribu satu pertanyaan.”
- “Suara malas dewa-dewa kekenyangan.”
- “Cerita itu meninggalkan bekas di wajahnya.”
- “Kabut melayang, pendar bulan samar-samar.”
- “Angin bertiup, dan kabut tersingkap dari wajah bulan.”
- “Jesus Maria adalah mercusuar perikemanusiaan.”
- “Mata si Manis terselubung kabut ajakan.”
- “Suaranya semanis dengungan kumbang.”
- “Mereka bangun dengan gerakan selembut gelembung sabun yang baru keluar dari pipanya.”
- “Matahari berhasil menembus mega yang mengungkungnya.”
- “Berdebat dengan diri sendiri.”
- “Kesunyian yang meraung-raung.”
Tak jarang, kalimat-kalimatnya juga begitu filosofis, seperti berikut ini:
- “Kesedihan adalah ibu semua perasaan lainnya.”
- “Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga.”
- “Mereka tidur nyenyak, sebab bantal yang terbaik adalah hati nurani yang tenteram damai.”
- “Kau duduk bagai orang pertama sebelum dunia ini tumbuh dewasa, dan bagai orang terakhir saat dunia ini telah mati.”
- “Cakar-cakar kasar petualangan secara kejam telah mencengkeram jiwanya.”
- “Hidup telah meninggalkanmu.”
Terakhir, yang jangan sampai terlewatkan, yaitu leluconnya. Entah bagi kalian lucu atau tidak, saya akan tetap menuliskannya bahwa ada seorang nyonya dengan delapan orang anaknya serta ibunya yang tua renta tinggal dalam sebuah pondok di tepi jurang. Ibunya begitu tua, kisut, dan ompong. Ia adalah sisa dari generasi terdahulu, dan hampir tidak ada yang ingat kalau nama nenek-nenek itu adalah Angelica. Sebulan sekali si Nenek pergi ke gereja untuk pengakuan dosa. Tentu menarik jika mendengarkan dosa wanita tua ini. Karena, kapan si Nenek punya waktu untuk berbuat dosa? Rumah tempatnya tinggal begitu penuh dengan bocah yang merangkak, merayap, tertatih-tatih, menjerit-jerit, pencekik kucing, suka jatuh dari pohon, dan setiap dua jam bocah-bocah itu merasa kelaparan. Tak mengherankan bila si Nenek punya saraf sekeras baja dan tak mudah tergoda dosa. Bila bukan si Nenek, sudah pasti nyawanya melesat terbang.
Si Nyonya, yang bernama Teresina Cortez, wanita yang cukup membingungkan jika dipandang dari cara berpikirnya...
Ah, sudahlah, saya takkan melanjutkan ceritanya. Biar kalian membacanya sendiri di sub-judul “Danny dan Kawan-kawannya Menolong Seorang Nyonya”. Intinya, bocah-bocah putra Teresina itu bertebaran di lantai, dan sering mengejar-ngejar kacang polong yang dilemparkan oleh si Nenek.
Selain kisah tentang Nyonya Teresina—yang saking suburnya, suatu waktu pernah melahirkan bocah di lapangan sepakbola—adapula kisah tentang si Manis yang sering pamer dengan mesin pengisap debunya. Tiap sore hari, si Manis mondar-mandir mendorong mesin pengisap debu, dan mulutnya menirukan suara deruman mesin. Di Dataran Tortilla memang tak ada yang memiliki mesin pengisap debu selain si Manis, sebab listrik pun belum menjamah daerah itu.
Cerita konyol si Manis bisa dinikmati pada bagian “Danny Terpikat oleh Mesin Pengisap Debu” Ah, pokoknya banyak cerita serta pelajaran yang bisa kita ambil dari Dataran Tortilla. Begitulah menurut saya.
Singkatnya—seperti yang tertulis di bagian belakang buku—Dataran Tortilla menggambarkan kehidupan kaum paisano. Dan Danny, seorang non-konformis, memimpin sekelompok petualang, hidup bersenang-senang, tanpa pertimbangan baik-buruk. Tapi sebuah tragedi yang menimpa kelompok petualang ini merupakan amanat pengarang yang halus mengenai nilai hakikat manusia dalam menghadapi nasib.
O ya, soal Dataran Tortilla, ternyata sudah banyak orang yang membincangkan dan menuliskan kesannya tentang buku itu. Kalian bisa meniliknya di blog Anggur Torelli. Di situ ada lebih dari satu-dua tulisan yang membahas tentang Dataran Tortilla. Mereka ramai membicarakan dan menuliskannya pada tahun 2012. Sebab, buku itu pun memang sudah dicetak sejak lama. Terjemahan pertamanya dicetak pada tahun 1977, dan cetakan kedua tahun 2009. Jadi, saya memang orang yang terlambat. Lebih-lebih yang sampai saat ini belum membacanya. Tapi, bukankah lebih baik telat daripada telat banget?
Selamat berburu; selamat bertamasya di Dataran Tortilla.
Purwokerto, Juli 2015




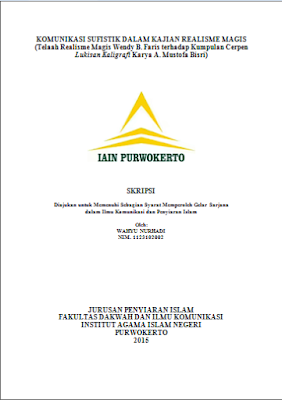
Comments